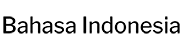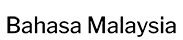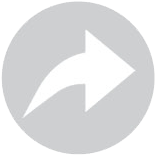Indonesia Waspadai Anak-anak Deportan ISIS
2018.05.07
Nusa Dua
 Kepala BNPT, Suhardi Alius berbicara kepada wartawan usai membuka workshop Global Counter Terrorism Forum di Nusa Dua, Bali, 7 Mei 2018.
Kepala BNPT, Suhardi Alius berbicara kepada wartawan usai membuka workshop Global Counter Terrorism Forum di Nusa Dua, Bali, 7 Mei 2018.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkirakan sekitar 1.000 anak simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), yang kembali ke Indonesia setelah dideportasi saat hendak masuk Suriah, rentan menjadi kelompok radikal atau bahkan pelaku terorisme sehingga perlu diwaspadai.
Kepala BNPT Komjen. Pol. Suhardi Alius menyampaikan fakta itu setelah membuka lokakarya bertema Inisiatif untuk Mengatasi Tantangan Kembalinya Keluarga Pejuang Teroris Luar Negeri atau Initiative on Addressing the Challenge of Returning Families of Foreign Terrorist Fighters di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Senin, 7 Mei 2018.
Lokakarya yang diadakan oleh Global Counter Terrorism Forum (GCTF) diikuti 30 negara anggota, termasuk Australia, Amerika Serikat, Belanda, Turki, Pakistan, dan Perancis. Selain pemerintah, hadir wakil organisasi masyarakat sipil dan akademisi.
Menurut Suhardi, saat ini sejumlah negara sedang menghadapi kembalinya pejuang teroris warga asing atau Foreign Terrorist Fighters (FTF) setelah kekalahan kelompok ekstremis di Suriah dan Irak.
“Meskipun ISIS telah kalah di Suriah dan Irak, kembalinya FTF mengakibatkan kian dekatnya ancaman ke kawasan kita, termasuk Indonesia,” katanya.
Suhardi mengatakan jumlah WNI yang dideportasi lebih dari 500 keluarga. Mereka adalah keluarga yang sudah meninggalkan Indonesia menuju Suriah tapi tidak bisa masuk dan dideportasi dari Turki.
“Kami sudah ke perbatasan Turki dan Suriah agar mereka bisa kasih informasi awal agar bisa kita pantau,“ ujarnya.
Dengan asumsi satu keluarga memiliki dua anak, tambahnya, maka ada lebih 1.000 anak dari anggota ISIS yang kembali ke Indonesia.
Mereka tersebar setidaknya di 40 kota terutama di Jawa dan Sumatera serta sebagian kecil di Sulawesi dan Kalimantan.
Jumlah itu menambah daftar panjang orang-orang yang potensial menjadi radikal atau bahkan menjadi teroris.
Saat ini, menurut Suhardi, ada sekitar 600 mantan napi kasus terorisme. Artinya, ada sekitar 1.200 anak yang juga harus diperhatikan.
Contohnya anak salah seorang pelaku Bom Bali tahun 2002, Imam Samudera. Saat bapaknya melakukan pengeboman, dia masih enam tahun, tetapi 12 tahun kemudian dia ikut bertempur di Suriah dan mati di sana.
“Ini kesalahan siapa? Kita bersama karena tidak bisa mendeteksi,” kata Suhardi.
“Mereka juga perlu kita monitor, bukan justru didiskriminasi. Anak-anak mereka yang mendapat stigma sebagai anak teroris, mereka harus diselamatkan agar tidak frustasi. Anak-anak ini adalah korban. Mereka tidak mengerti tetapi diajak orang tuanya menuju Suriah yang kemudian dilabelisasi dan dimarjinalkan,” lanjutnya.
Fenomena global
Lars Tummers, Utusan Khusus Pemberantasan Terorisme dari Belanda menyatakan, dengan kekalahan ISIS dan kembalinya FTF, isu anak-anak menjadi fokus penting.
Ketika para laki-laki mungkin terus berperang atau berpindah ke medan konflik baru, para perempuan yang ketakutan atau kecewa, akan kembali pulang bersama anak-anak mereka.
“Sejauh ini, mereka belum kembali dalam jumlah besar. Mereka hanya serupa tetesan air. Namun, harus kita ingat bahwa masih banyak perempuan dan anak-anak yang terjebak di antara garis militer maupun tinggal di kamp-kamp,” katanya.
Menurut Tummers, sangat sulit memperkirakan jumlah sesungguhnya mereka yang kembali bersama keluarga dan tiap negara akan memiliki jumlah berbeda.
Sebagai contoh, dia menyebut setidaknya ada 175 warga terhubung dengan Belanda yang berada di Suriah dan Irak. Lebih dari dua pertiga mereka baru lahir selama berada di negara konflik tersebut.
“Ini merupakan tantangan yang sangat kompleks. Anggota keluarga, terutama anak-anak, membutuhkan dukungan dan perhatian, tetapi mereka juga mungkin meningkatkan risiko,” tuturnya.
“Hampir 10 persen dari warga Belanda di Suriah dan Irak sudah berumur 9 tahun, usia di mana anak-anak anggota ISIS sudah berlatih perang dan oleh karena itu mereka juga bisa berpotensi menjadi ancaman nasional.”
Pendekatan seimbang
Bagi Indonesia, tantangan kembalinya keluarga FTF juga membutuhkan pendekatan seimbang antara penegakan hukum dan upaya pencegahan – yang menjadi tulang punggung keberhasilan merespon tantangan kembalinya keluarga FTF.
Penegakan hukum, seperti penuntutan dan pengadilan bagi keluarga FTF, menurut Suhardi, tak akan menciptakan hasil berkelanjutan.
Karena itu, program yang fokus pada deradikalisasi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi keluarga FTF menjadi hal penting untuk menciptakan hasil berkelanjutan.
Keberhasilan Indonesia menangani keluarga FTF yang kembali, katanya, tak hanya karena penegakan hukum semata tapi juga keterlibatan kementerian lain.
Dia mencontohkan anak Amrozi yang pernah belajar membuat bom saat berusia 10 tahun untuk membalas dendam atas eksekusi mati ayahnya, tapi kini sudah menjadi bagian dari program rehabilitasi dan reintegrasi di Lamongan, Jawa Timur.