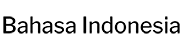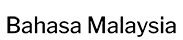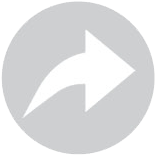Ketua AMSI: Indonesia perlu undang-undang untuk mengatur ekosistem digital
2022.10.20
Jakarta
 Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut saat diwawancara BenarNews di Jakarta, 29 September 2022.
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut saat diwawancara BenarNews di Jakarta, 29 September 2022.
Dalam wawancara dengan BenarNews, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mendorong pemerintah membuat undang-undang untuk mengatur ekosistem digital di Indonesia, dimana surplus informasi, hoaks, dan media sosial melemahkan jurnalisme dan membuat berita yang otentik menjadi kurang relevan.
Jurnalisme Indonesia mengalami kematian perlahan karena teknologi digital telah menyebabkan media beralih fokus pada berapa banyak sebuah laman dibuka tanpa memperhatikan kualitas konten, kata Wenseslaus Manggut, ketua umum asosiasi yang dideklarasikan pada 2017 dan beranggotakan lebih dari 410 perusahaan media siber di Tanah Air.
Wens – panggilan akrab Wenseslaus – mengatakan bahwa dalam ekosistem sekarang ini, jurnalisme di Indonesia kalah oleh surplus disinformasi, ujaran kebencian dan hoaks yang disebarkan melalui platform besar, seperti Google, Facebook, Instagram, dan Twitter.
Oleh karena itu, Wens menegaskan, pemerintah perlu membuat undang-undang yang mengatur sektor hulu dari ekosistem digital di Indonesia untuk mengganti atau melengkapi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008.
“Saya selalu bilang bahwa UU ITE itu pemadam kebakaran, ada api hoaks padamkan, ada api hate speech padamkan. Pemerintah kita dalam urusan seperti itu. Padahal dia levelnya negara, dengan level negara in harusnya bisa menata instalasi digitalnya supaya tidak terjadi kebakaran bukan sekedar memadamkan apinya doang,” kata Wens kepada BenarNews dalam sebuah wawancara baru-baru ini di Jakarta.
Berikut petikan wawancaranya:
![Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia Wenseslaus Manggut 2.jpg Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wenseslaus Manggut saat diwawancara di Jakarta, 29 September 2022. [Eko Siswono Toyudho/BenarNews]](/indonesian/berita/amsi-undang-undang-untuk-mengatur-ekosistem-digital-10202022140228.html/ketua-asosiasi-media-siber-indonesia-wenseslaus-manggut-2.jpg/@@images/9c42333d-a4d1-4beb-9dd7-b7e9b80241a5.jpeg)
Q: Digitalisasi pada awalnya adalah sebuah solusi bagi jurnalisme. Solusi dari terbatasnya publik mengakses informasi. Tapi ternyata sekarang yang terjadi adalah polusi informasi di Indonesia. Kenapa?
Saya kira memang ada masalah di industri hulunya. Kita dengan teman-teman platform seperti Google, Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain harus punya pemahaman yang sama bahwa freedom of speech (kebebasan berpendapat), yes. Tetapi ada dampak dari itu terutama di dalam ekosistemnya, lalu solusi kita seperti apa.
Seperti yang dilakukan oleh negara-negara Eropa yang bertemu di Kopenhagen, yang diinisiasi Denmark. Mereka mengklasifikasikan menjadi tiga.
Pertama, hak publisher atas konten. Konten itu clear merupakan intellectual property rights (hak kekayaan intelektual). Karena menulis berita itu yang harus menaati sekian kode etik itu, tidak sama seperti membuat barang yang sudah ada prototype-nya.
Karena ketika seseorang membuat berita dia harus berpikir. Dia harus menggunakan data, harus menggunakan klarifikasi dan dia juga harus menggunakan cara dan metrik. Baru jadilah sebuah berita. Jadi ada unsur intelektual di dalamnya.
Kalau dalam versinya Denmark siapa pun tidak boleh memakai berita ini tanpa melakukan perjanjian kerja sama dengan publisher (penerbit), termasuk perusahaan platform tidak boleh sembarang menggunakan konten kita di platform mereka.
Jadi ini seperti melawan takdirnya ekosistem yang ada sekarang. Karena ekosistem yang ada sekarang makin banyak disebar makin menguntungkan.
Kedua, hak publisher atas data. Waktu orang-orang itu membaca lalu profiling mereka terdata, “Oh, ini perempuan, dan ini laki-laki. Dia ini membaca politik, membaca ekonomi, membaca lifestyle. Lalu terhimpun menjadi sebuah data mining yang besar.
Lalu data ini milik siapa? Menurut teman-teman ini, data itu milik publisher. Karena data terhimpun dari mereka yang membaca konten publisher di platform.
Ketiga adalah sisi bisnis. Sisi bisnis ini karena intellectual property rights siapapun tidak boleh mentransaksikan hak kepemilikan intelektual ini tanpa perjanjian kerja sama. Itu tiga poin yang mereka perjuangkan.
Langkah yang telah diambil praktisi media digital Indonesia apa?
Indonesia harus punya undang-undang yang meregulasi platform. Jerman, misalnya, menyadari itu lalu mereka membuat UU media sosial, NetzDG, yang kira-kira dapat mengatur platform bila ada berita hoaks dalam waktu 24 jam Anda akan mendapat denda.
Di Indonesia yang seperti ini kita berharap dijaga oleh UU ITE tapi undang-undang ini keywords pertamanya adalah transaksi. Didalam kebebasan berpendapat sepertinya janggal kata-kata transaksi itu ada.
Mungkin kalau dirunut UU ITE ini mengatur orang-orang di e-commerce karena di situ ada transaksi dan kita tidak ada regulasinya. Tetapi by the way UU ITE ini mengatur audiens atau mengatur penumpang. Saya sering sekali pakai kata perumpamaan penumpang dalam sebuah bus.
Jadi UU ITE di Indonesia itu mengatur penumpang bukan mengatur bus pengangkut penumpang. NetzDG Jerman itu mengatur busnya.
Apa bedanya?
Mengatur penumpang itu selalu post factum (sesudah kejadian). Hoaks-nya sudah menyebar dulu, hate speech-nya naik dulu. Damage (kerusakan)-nya sudah terjadi dulu. Akibatnya orang demo dan membakar fasilitas publik. Baru orangnya ditangkap tapi kerusakan sudah terjadi. UU ITE post factum di situ.
Bedanya dengan NetzDG Jerman menindak di hulunya. Kalau di hulunya teman-teman platform yang diatur, jadi mereka mencari cara supaya hoaks itu tidak beredar atau ditekan reach dan penyebarannya.
NetzDG ini lebih kepada bagaimana platform mengantisipasi konten sampah di tempat mereka. Biasanya proses itu harus ada report dari 200 orang. Kalau tidak sampai 200 orang berarti belum sampai pada alert human.
Jadi kalau kontennya seperti saat ini bagaimana nasib media sekarang?
Kalau kita tidak melakukan sesuatu, maka industri medianya akan tergiring dalam ekosistem yang sekarang.
Bikin aja konten receh, konten sadur, konten click bait jauh lebih menguntungkan dari pada menaati sekian metrik, atau poin undang-undang pers, atau kode etik jurnalistik tidak ada untungnya menaati itu. Lebih bak menaati cara kerja teman-teman ini itu yang pertama.
Ini yang Anda pernah katakan sebagai jurnalisme sudah mati sekarat?
Sebetulnya mati dalam ekosistem yang sekarang ini. Saya dan Anda datang dari ekosistem jurnalisme yang kita jaga betul itu, dan beruntungnya itu kita juga mengetahui ekosistem yang sekarang terjadi.
Di dalam ekosistem yang sekarang ini di mana insentif ekonomi datang dalam metrik yang tidak mengukur konten, kita dengan sederhana berbicara seperti ini.
Semua lembaga ukur yang menjadi benchmark dalam bisnis ini, tidak mengukur konten tetapi mereka mengukur audiens. Jumlah pembaca berapa, pageview-(jumlah laman yang dibuka)nya berapa tetapi tidak mengukur kontennya. Dan mereka harus mengukur bagaimana kerja kita, harus mengukur siapa kita.
Apakah kontennya orisinal atau tidak. Apakah kontennya memenuhi kaidah jurnalistik atau tidak. Apakah kontennya itu tidak ada unsur hate speech atau tidak. Apakah kontennya menyadur atau tidak. Mereka tidak mengukur itu.
Jadi semua lembaga ukur yang menentukan nasib kita di industri ini tidak pernah mempertimbangkan jurnalisme dalam metrik mereka.
Karena pageview menentukan feeding iklan. Mereka membuat rangking bagi media based on berapa jumlah yang baca dan tidak melihat kontennya.
Seberapa mendominasi platform ini dalam ekosistem media di Indonesia?
Delapan puluh persen platform yang menguasai jalur distribusi konten. Mereka punya cara pikirnya sendiri. Dulu mereka hanya sebagai transmiter saja, mentransmisi konten kita ke publik. Platform hanya memindahkan saja.
Lalu kemudian platform mulai melakukan fungsi distribusi. Perlahan-lahan mereka menggunakan algoritma, Setelah melakukan fungsi distribusi, berikutnya adalah melakukan fungsi monetisasi.
Algoritma itu menjadi penentu bagi distributor dalam menentukan seberapa luas, atau seberapa banyak, seberapa cepat jangkauan konten-konten kita, termasuk reach atau sebarannya.
Seharusnya algoritma solusi bagi industri media dan kebebasan pers?
Algoritma punya cara pikirnya sendiri. Dalam konteks industri media mungkin baik. Karena membantu memonetisasi konten. Tapi tidak begitu bagi kebebasan pers dan kebebasan mendapatkan informasi.
Banyak ahli bilang bahwa kebebasan mendapatkan informasi pada zaman sekarang sepenuhnya tidak bebas juga, karena kebebasan itu datang dalam wujud algoritma.
Algoritma itu menyangkut jejaknya kita. Kalau kita suka baca A terus kita kan di-feeding konten A terus. Kita sebetulnya dikurung dalam konten dunia A itu.
Padahal hakikatnya freedom itu adalah terbuka dengan sekian banyak perspektif. Tetapi algoritma bisa mengurung kita dalam satu perspektif karena dia membaca interest dan jejaknya kita di situ.
Dengan begitu, maka algoritma semakin penting bagi dunia pers. Jika tidak memahami algoritma itu bisa membuat kita pingsan sebagai perusahaan pers. Jurnalisme mungkin hidup tapi perusahaannya bisa mati.