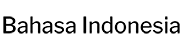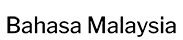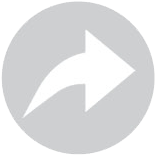Melawan Diskriminasi Terhadap Penganut Kepercayaan
2018.02.01
Jakarta
 Dari kiri ke kanan: Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, peneliti SETARA Sudarto dan Halili saat jumpa pers di Jakarta, 31 Januari 2018.
Dari kiri ke kanan: Wakil Ketua SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos, Ketua Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI) Engkus Ruswana, peneliti SETARA Sudarto dan Halili saat jumpa pers di Jakarta, 31 Januari 2018.
Masih teringat jelas di benak Engkus Ruswana kesulitan yang dialami keluarganya ketika mengurus pemakaman ibunya yang meninggal dunia, tahun 2003.
Sebelum berpulang, sang ibu yang tinggal di Bandung berwasiat agar jenazahnya dimakamkan di kampung kelahirannya di Panjalu, Ciamis, Jawa Barat.
Engkus pun berkomunikasi dengan keluarga di Ciamis agar minta dipersiapkan liang lahat dan prosesi pemakaman.
Namun, iringan pengantar jenazah ditahan ustadz setempat, yang melarang jenazah ibunya dikuburkan di tanah kelahirannya karena bukan Muslim. Keluarga Engkus adalah penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan.
Pihak keluarga pun menggelar rapat dengan tokoh-tokoh agama untuk membahas prosesi pemakaman, sementara jenazah ibu tak boleh keluar dari ambulans. Akhirnya kesepakatan dicapai.
“Ibu bisa dikubur asal disalatkan dulu. Mayatnya di-Islam-kan dulu agar bisa dikubur,” ujar Engkus, yang kini menjabat Ketua Umum Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI), kepada BeritaBenar di Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018.
“Kami pasrah, ya harus bagaimana. Tentu sedih. Tapi kami tidak bisa apa-apa. Dipaksa untuk menganut.”
Engkus menilai kejadian itu adalah contoh dari sekian banyak diskriminasi yang diterimanya, bersama keluarga dan para penghayat kepercayaan di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 November 2017 yang membolehkan aliran kepercayaan dicantum di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP) dinilai Engkus adalah terobosan baru untuk menjamin hak-hak konstitusional mereka sebagai warga negara.
“Ada beberapa yang sudah diisi di kolom agama. Kalau saya masih dikasih tanda strip. Kami butuh pengakuan negara. Selama ini, kalau KTP dikosongkan berarti tidak diakui, dianggap tidak beragama, tidak ber-Tuhan,” ujar Engkus.
Sejak penjajahan
Organisasi yang bergerak riset dan advokasi di bidang demokrasi, kebebasan berdemokrasi dan hak asasi manusia, Setara Institute, memotret diskriminasi atas agama lokal Nusantara telah terjadi sejak zaman penjajahan kolonial Belanda yang berlanjut hingga kini.
“Pemerintah Belanda memberikan keistimewaan untuk agama-agama besar dan otomatis menegasikan penganut agama lokal,” ujar peneliti Setara, Sudarto, saat peluncuran laporan Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.
“Hal ini berlanjut ketika pemerintah Indonesia mulai mendefinisikan arti agama, yakni harus memiliki kitab suci, nabi, dan pengikut di berbagai negara. Penganut kepercayaan dipaksa memeluk agama-agama besar ini sambil tetap mengerjakan ritual agama-agama lokal. Di sinilah potensi munculnya 'penistaan agama'.”
Lalu, negara membuat sejumlah aturan yang justru memperkuat potensi diskriminasi terhadap penghayat.
“Secara eksplisit menganggap kelompok penghayat sebagai bagian pengacau keamanan,” katanya.
Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan keputusan MK bersifat final dan pemerintah terikat untuk melaksanakannya.
Namun, lanjutnya, dalam pelaksanaan timbul masalah karena sebagian pihak menganggap proses sidang MK bermasalah karena tidak menghadirkan organisasi keagamaan, khususnya Islam, untuk memberikan tanggapan sebagai pihak terkait.
“Beberapa pihak menilai proses hukum tersebut memiliki kelemahan,” jelas Mu’ti kepada BeritaBenar.
Menurutnya, putusan MK hanya terkait penulisan Aliran Kepercayaan di KTP bukan terkait dengan kedudukan Aliran Kepercayaan. Masyarakat memahami pasal 29 ayat 2 UUD 1945 jelas membedakan agama dan kepercayaan.
“Sebagian masyarakat memahami ‘kepercayaan’ dalam UUD 1945 merupakan bagian dari agama. Dalam konteks Islam, ‘kepercayaan’ dimaknai seperti madzhab atau aliran. Karena itu, kedudukan aliran kepercayaan tidak sama dengan agama, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak sipil sebagaimana pemeluk agama,” tegas Mu’ti.
Dia juga menilai pemerintah tidak cukup percaya diri melaksanakan keputusan MK karena beberapa alasan.
“Tidak ada definisi agama yang resmi dikeluarkan negara, belum ada payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan, dan faktor politik dimana pemerintah kehilangan dukungan dari mayoritas masyarakat,” ujarnya.
“Menjelang Pemilu dan Pilpres 2019 faktor politik ini cukup kuat.”
Memotong diskriminasi
Untuk memotong rantai diskriminasi, Setara mengusulkan beberapa langkah mendesak dalam upaya melindungi hak-hak konstitusional penganut kepercayaan.
Pertama, pemerintah harus sepakat apakah mau mencantumkan seluruh agama yang ada, dicatat satu persatu atau konsisten mengikuti pasal 29 UUD 1945 tentang “Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
“Itu yang disepakati tapi harus ada penegasan bahwa selain enam agama yang ada, ada juga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,” ujar Sudarto.
“Yang terpenting sosialisasi. Banyak daerah tak serta-merta dapat menerima keputusan ini, terutama daerah-daerah yang selama ini sudah mapan dengan basis agama sudah kuat, ini berat sekali.”
Setelah itu, lanjut Sudarto, perlu dilakukan revisi banyak peraturan dan undang-undang, yang menyebutkan penghayat aliran kepercayaan sebagai pengacau keamanan.
“Pengakuan terhadap agama lokal bukanlah hadiah dari Mahkamah Konstitusi atau negara. Negara harus menghargai. Ini disebut given,” imbuhnya.
Engkus meminta lembaga-lembaga negara dan organisasi-organisasi keagamaan lain untuk membantu menghentikan diskriminasi terhadap penghayat kepercayaan.
“Harapan kami mereka membuka hati untuk menerima kami para penghayat kepercayaan. Jangan ada lagi melakukan diskriminasi terhadap kami. Apalagi, agama-agama lokal sudah ada terlebih dahulu dibandingkan agama-agama besar,” pungkasnya.