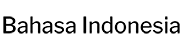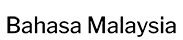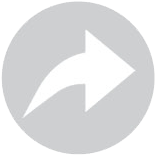Penahanan Duterte bawa harapan bagi korban rejim otoriter Asia Tenggara
2025.03.17
Washington
 Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terlihat di lokasi yang disebut sebagai Pangkalan Udara Villamor di Metro Manila, setelah dia ditangkap berdasarkan surat perintah dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) , dalam gambar yang diambil dari video media sosial, 11 Maret 2025.
Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terlihat di lokasi yang disebut sebagai Pangkalan Udara Villamor di Metro Manila, setelah dia ditangkap berdasarkan surat perintah dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) , dalam gambar yang diambil dari video media sosial, 11 Maret 2025.
Penangkapan mantan Presiden Filipina minggu ini berdasarkan surat perintah dari Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akan membuat “Hun Sen tidak bisa tidur,” kata seorang kritikus mantan Perdana Menteri Kamboja.
Kritikus tersebut, Kim Sok, yang tinggal di pengasingan, menyuarakan optimisme bahwa keadilan sedang ditegakkan kepada para pemimpin Asia Tenggara dulu dan sekarang yang diduga terlibat pelanggaran hak asasi manusia serius seperti Rodrigo Duterte dari Filipina dan Hun Sen dari Kamboja.
Namun, beberapa pengamat tetap mempunyai pandangan suram terhadap para korban persekusi politik atau rasial di kawasan tersebut.
Penangkapan Duterte pada hari Selasa untuk menghadapi persidangan atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukannya selama perang melawan narkoba ilegal menunjukkan potensi bahwa ICC akan meminta pertanggungjawaban para pemimpin, ujar pakar hukum internasional Indonesia, Eddy Pratomo.
“Pemerintah Filipina saat ini, di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr. bekerja sama dengan Interpol, dan membuat penangkapan (Duterte) menjadi mungkin,” kata Eddy, seorang pakar ICC dan profesor di Universitas Diponegoro di Semarang, kepada BenarNews.
“Ini adalah skenario yang langka, karena banyak negara, terutama yang memiliki pemimpin aktif yang dituduh melakukan kejahatan, menolak untuk bekerja sama dengan ICC. … Bagi negara berdaulat dengan sistem hukum yang kuat, jangkauan ICC terbatas,” tambahnya.

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menghadiri pertemuan dengan pemimpin ASEAN dan perwakilan komunitas bisnis AS, sebagai bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN-AS di Washington, 12 May 2022. (Elizabeth Frantz/Reuters)
Eddy merujuk pada apa yang banyak dilihat sebagai penangkapan ICC yang terkait dengan politik Filipina.
Pada tahun 2022, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. maju dalam pemilihan umum nasional bersama Sara Duterte, putri dari Duterte, tapi sekarang Marcos berselisih dengan Sara dan keluarganya.
Pemerintah Marcos membantu Interpol menindaklanjuti surat perintah ICC dengan mengirim polisi untuk menangkap Duterte.
Marcos Jr. adalah putra mendiang Presiden Filipina Ferdinand E. Marcos, yang mengumumkan darurat militer di negara itu pada tahun 1972. Selama menjabat, mendiang Marcos Senior menjebloskan 70.000 orang ke penjara, 34.000 disiksa, dan lebih dari 3.200 orang dibunuh, menurut Amnesty International.
Namun berbeda di Kamboja. Menurut Kim Sok, calon perdana menteri di masa yang akan datang, walau diusung oleh partainya Hun Sen, ia tidak akan dilindungi jika ICC mengeluarkan surat perintah untuk menangkap mantan orang kuat Kamboja tersebut. Perdana Menteri yang sedang menjabat sekarang, Hun Manet, adalah putra Hun Sen.
"Walaupun perdana menteri selanjutnya berasal dari partai penguasa - Cambodians People's Party- , mereka akan membuka jalan untuk penangkapannya, karena bila mereka tidak bekerja sama, mereka akan terlibat dalam kejahatan yang dilakukan Hun Sen," ujar Kim Sok kepada Radio Free Asia, kantor berita yang terafiliasi dengan BenarNews.
"Perkembangan ini akan membuat Hun Sen tidak bisa tidur selamanya," tambah Kim Sok, yang pergi mengasingkan diri di 2018 karena kawatir akan keselamatan dirinya bila terus berada di Kamboja.
Lembaga advokasi hak asasi manusia berbasis di New York, Human Rights Watch, mencatat pada 2015 bahwa Hun Sen terlibat dengan "pembunuhan ekstra yudisial, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang, pengadilan kilat, penyensoran, larangan berkumpul dan berasosiasi, serta jaringan mata-mata dan informan nasional yang bertujuan untuk menakut-nakuti dan mengintimidasi masyarakat agar tunduk.”

Panglima TNI Jenderal Wiranto (kiri) membetulkan tanda pangkat Letnan Jenderal Prabowo Subianto saat itu, dalam sebuah upacara militer di Jakarta, 28 Mei 1998. (Reuters)
Seperti keluarga Marcos, keluarga Duterte dan keluarga Hun Sen yang telah melahirkan dinasti politik, Indonesia tahun lalu juga memilih presiden dan wakil presiden yang terkait dengan klan politik.
Terpilihnya Prabowo Subianto sebagai presiden Indonesia, setelah kemenangan Marcos Jr. dan Sara Duterte pada tahun 2022, membuat kolumnis BenarNews Zachary Abuza menyatakan adanya semacam “amnesia historis” di Asia Tenggara.
Prabowo mempunya hubungan keluarga langsung dengan mantan presiden Suharto. Dia pernah menikah dengan putri mendiang diktator yang memerintah Indonesia dengan tangan besi selama 32 tahun.
Suharto meraih kekuasaan setelah pemberantasan brutal terhadap komunisme di tahun 1960-an. Asumsi umum yang beredar menyebutkan bahwa Suharto menyetujui pembunuhan sekitar 500.000 hingga 1 juta orang, dan pada tahun 1998 memerintahkan penindasan dengan kekerasan terhadap protes mahasiswa.
Prabowo, seorang mantan jenderal Angkatan Darat dituduh terkait atau mengatur beberapa pelanggaran hak asasi manusia selama karier militernya. Namun, tidak ada tuduhan yang pernah diajukan terhadapnya atau diadili di pengadilan.

Panglima militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing menghadiri upacara peletakan karangan bunga di Makam Prajurit Tak Dikenal di dekat Tembok Kremlin di pusat kota Moskow, 4 Maret 2025. (Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters)
Bedjo Untung, seorang penyintas pemberantasan antikomunis, dipenjara sembilan tahun dalam tahanan militer di bawah rezim Suharto dan menjalani kerja paksa dan penyiksaan.
"Saya merasa ada dukungan dengan berita penangkapan Duterte. Seorang mantan presiden dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang,” ujar Bedjo, yang merupakan ketua Yayasan Advokasi Korban 1965, kepada BenarNews.
“Ini memberi saya harapan bahwa keadilan juga dapat ditegakkan di Indonesia, di mana impunitas telah berlaku selama hampir 60 tahun. Kami telah diabaikan selama beberapa dekade.”
Pada bulan November, Jaksa ICC Karim A.A. Khan memutuskan untuk meminta surat perintah penangkapan untuk kepala militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing atas hubungannya dengan dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap minoritas Rohingya, dari Agustus sampai Desember 2017.
Militer dan polisi Myanmar pada tahun 2017 membunuh puluhan ribu Muslim Rohingya yang teraniaya sebagai tanggapan atas serangan oleh pemberontak dari kelompok tersebut terhadap pos polisi dan tentara di negara bagian Rakhine.
Saat ini Min Aung Hlaing masih menjadi kepala militer dan pemimpin Myanmar. Pada Februari 2021, sang jenderal menggulingkan pemerintahan yang terpilih.

Mohammed Taher, seorang pengungsi Rohingya menggendong putranya Mohammed Shoaib, yang ditembak di dada sebelum menyeberangi perbatasan dari Myanmar, saat mereka berdiri di luar sebuah klinik medis, di kamp pengungsi Kutupalong dekat Cox's Bazar, Bangladesh, 5 November 2017. (Adnan Abidi/Reuters)
Tun Khin, pendiri Burmese Rohingya Organization UK, yang mengajukan gugatan terhadap para pemimpin militer Myanmar di pengadilan Argentina, mengatakan bahwa ia senang mendengar tentang Duterte.
"Siapa pun dapat melakukan kejahatan, tetapi tidak seorang pun dapat lolos dari keadilan. Pada akhirnya, Anda akan ditangkap," katanya kepada RFA Burmese.
"Meskipun (Min Aung Hlaing) saat ini memegang kekuasaan secara ilegal, akan tiba saatnya, baik saat ia tidak lagi berkuasa atau jika ia bepergian ke luar negeri, ia akan ditangkap. Penangkapan Duterte menjadi peringatan yang jelas bagi para pemimpin militer Myanmar."
Sementara itu, sebagian besar pemerintahan di Asia Tenggara tetap bungkam mengenai penangkapan Duterte.
Ketika BenarNews meminta tanggapan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Rolliansyah Soemirat mengatakan, "Kami tidak berkomentar mengenai masalah ini."
Juru bicara pemerintah Thailand Jirayu Huangsap mengatakan bahwa Bangkok tidak akan memberikan tanggapan. "Ini masalah politik internasional. Ini bukan urusan Thailand, jadi kami tidak bisa berkomentar," katanya kepada BenarNews.
‘Budaya ASEAN’
Analis Thailand Thanaporn Sriyakul mengatakan para pemimpin Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) bungkam “karena mereka tidak ingin terjebak dalam baku tembak.”
Anon Nampa, seorang pemimpin protes antipemerintah pada tahun 2020, mengunjungi sebuah pameran selama peringatan 44 tahun pembantaian mahasiswa prodemokrasi oleh pasukan negara di Universitas Thammasat di Bangkok, 6 Oktober 2020. (Jorge Silva/Reuters)
Di Thailand, mereka yang berkuasa, baik dari pemerintah terpilih maupun militer, “dengan tegas mempertahankan” budaya impunitas, kata Thanaporn, ketua Asosiasi Ilmu Politik di Universitas Kasetsart.
“Itulah sebabnya kami tidak melihat adanya tindakan yang diambil dalam kasus-kasus seperti pembantaian Tak Bai pada tahun 2004 atau pembantaian 6 Oktober 1976 … Tidak ada pemimpin tingkat tinggi yang pernah dimintai pertanggungjawaban atas masalah-masalah ini.”
“Oleh karena itu, mustahil bagi para pemimpin tingkat tinggi di Thailand untuk dituntut seperti Duterte.”
Pada 25 Oktober 2004 saat bulan suci Ramadan, 85 pengunjuk rasa tidak bersenjata tewas saat demo di depan kantor polisi di Tak Bai, di provinsi Narathiwat yang mayoritas penduduknya Muslim.
Pada bulan Oktober 1976, lebih dari 40 orang tewas dan lebih dari 150 orang terluka ketika polisi menyerbu kampus Universitas Thammasat di Bangkok untuk membubarkan demonstrasi ribuan mahasiswa yang memprotes kembalinya mantan penguasa militer, Thanom Kittikachorn.
“Mereka yang berkuasa di negara-negara ASEAN berbagi keuntungan bersama dan keuntungan yang saling terkait dalam satu atau lain cara,” kata Thanaporn dari Universitas Kasetsart.
“Budaya impunitas sudah menjadi budaya ASEAN.”