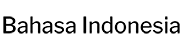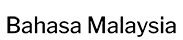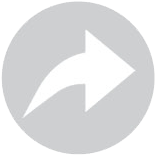Pakar: Intoleransi Meningkat Saat Pemilu
2017.05.02
Jakarta
 Para pembicara diskusi publik bertajuk ‘Kebencian Berbasis Agama dan Tantangannya bagi Demokrasi’ di Jakarta, 2 Mei 2017.
Para pembicara diskusi publik bertajuk ‘Kebencian Berbasis Agama dan Tantangannya bagi Demokrasi’ di Jakarta, 2 Mei 2017.
Siar kebencian atau hate speech dan intoleransi diyakini meningkat selama masa kampanye dan pemilihan umum, demikian disampaikan pakar jurnalisme regional, Cherian George, dalam diskusi publik dan bedah buku karyanya yang berjudul “Hate Spin” di Jakarta, Selasa, 2 Mei 2017.
“Intoleransi cenderung meningkat adalah persoalan nomor satu bagi demokrasi Indonesia, meskipun situasinya tidak seburuk di beberapa negara lain,” kata George, dalam acara yang dirangkai dengan diskusi bertajuk "Kebencian Berbasis Agama dan Tantangannya bagi Demokrasi" itu.
Fenomena tersebut jelas terlihat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini, demikian menurut George, yang menambahkan bahwa hate speech berakar pada intoleransi dan bermuara menjadi hate spin.
Isu intoleransi mampu menggiring Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, yang kalah dalam Pilkada Jakarta 19 April lalu, ke meja hijau dengan tuduhan melakukan penistaan agama Islam, karena pidatonya di Kepulauan Seribu, September 2016, yang menyitir ayat Al-Maidah.
“Namun kampanye hitam yang berlangsung selama pemilihan Gubernur Jakarta tak berarti ancaman serius terhadap demokrasi. Politisi tetap menjadi politisi. Mereka akan melakukan apapun untuk menang,” tambah George.
Buku George itu merupakan hasil risetnya di tiga negara dimana hate spin meningkat; yakni Amerika Serikat, India, dan Indonesia.
George mengatakan peningkatan intoleransi umumnya melibatkan kelompok-kelompok garis keras. Karena itu, katanya, sebaiknya masyarakat tidak membesar-besarkan dukungan kepada mereka.
“Sebaiknya mereka dibiarkan ikut dalam kompetisi politik,” ujar George.
Undang-undang (UU) yang ada, kata dia, justru memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok garis keras dan militan untuk menyerang kelompok lain.
“UU tersebut rentan disalahtafsirkan dan disalahgunakan,” ujarnya.
Gerakan-gerakan massa berbasis keagamaan, tambahnya, juga bukan sesuatu yang spontan dan irasional.
Seperti diketahui bahwa sejak tahun lalu hingga kini, terjadi berbagai gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta untuk menuntut proses hukum atas Ahok.
Bahkan, Jumat pekan ini, massa akan kembali turun ke jalan untuk menuntut Ahok dihukum penjara.
“Ini adalah strategi politik yang diatur dengan baik. Dan sejarah membuktikan bahwa hanya dengan nasionalisme sipil sebuah negara akan kokoh, tanpa harus ada pertumpahan darah, yang berarti adanya kesetaraan hak dan supremasi hukum,” ujar George.
“Kasus serupa juga terjadi di dua negara lain, yang mengantarkan Donald Trump ke kursi Presiden Amerika Serikat dan Narendra Modi menjadi Perdana Menteri India.”
Diyakini akan terulang
Dalam kasus Ahok, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mengatakan pasal 156 KUHP yang menjerat Gubernur Jakarta itu justru terkesan memihak.
“Karena orang-orang yang melakukan hinaan-hinaan pada dia (Ahok) tidak kena apa-apa. (Padahal) kita juga punya UU anti diskriminasi rasial dan etnis. Cuma tidak tahu kenapa polisi tidak pakai,” ujar Asfinawati dalam acara tersebut.
“Kuncinya negara, harus konsisten. Negara meneruskan kasus hate speech yang dijadikan penodaan agama, namun di sisi lain kalau ada orang melakukan diskriminasi ras dan etnis, ya harus diproses juga.”
Asfinawati memperkirakan kejadian serupa kemungkinan akan terus berulang hingga Pemilu 2019. Untuk itu, lanjutnya, negara perlu menghentikan upaya kriminalisasi pada korban hate speech.
“Sebetulnya penodaan agama yang terjadi bukan karena ada orang menodai agama, tapi ada orang memutarbalikkan, sehingga menimbulkan kebencian kepada korban. Kemudian korban ini dituduh menodai agama,” ujarnya.
Jika kriminalisasi berlanjut, ujarnya, banyak pihak yang akan terus-menerus menjadikan hate speech sebagai senjata dan yang paling berbahaya adalah swasensor di kalangan minoritas.
“Kaum minoritas tahu dia mudah kena ancaman dan dia melakukan swasensor. Saya kira demokrasi akan lebih terganggu kalau yang terjadi adalah swasensor,” ujar Asfinawati.
Pasal penodaan agama
George juga mengatakan pentingnya bagi pemerintah untuk menghapus pasal penodaan agama dalam hukum negara masing-masing.
“Itu menjadi sumber intoleransi selama ini,” ujarnya.
Hal ini diamini Asfinawati dengan menyatakan, “Kita bisa meniru beberapa negara, yang punya pasal blasphemy, tapi dimatikan dalam praktek, jadi mati suri, meskipun tidak dicabut oleh DPR.”
Menurut dia, perlu komitmen polisi dan Kementerian Agama untuk mengatakan hukum dan kasus-kasus yang ada mungkin sudah mencapai ratusan, tidak pernah ada kata sepakat apa itu penodaan agama.
“Jadi orang cuma pidato bisa kena penodaan agama, mengajar bisa kena penodaan agama. Itu karena berbahaya dan kita harus berkomitmen untuk mematisurikan pasal ini,” katanya.
Peran media
Intoleransi dan hate speech merebak tak lepas dari peranan hoax. Untuk memberantasnya, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Arif Zulkifli, punya cara sendiri.
“Saya kira yang paling mungkin adalah jangan ikut menyebarkan hate speech, meski dalam pelaksanaannya itu tidak gampang. Karena handphone di tangan itu memang godaan yang luar biasa,” ujar Arif.
Arif menawarkan alternatif lain dengan menyebutkan bahwa dalam Pilkada, semua isu atau berita buruk tentang kandidat, dianggap hoax, kecuali ada hal sebaliknya mengatakan itu.
“Jadi ada yang bisa membuktikan bahwa semua itu bukan hoax. Sebaliknya, semua berita baik tentang kandidat anggap saja benar, kecuali ada yang mengatakan sebaliknya,” ujarnya.