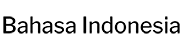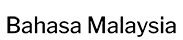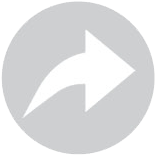Memetik Kearifan Lokal Kalimantan dalam Penyelesaian Konflik
2017.11.16
Pontianak
 Seorang pemuda Dayak melihat rumah milik orang Madura dibakar dekat Sampit, Kalimantan, 25 Februari 2001. Konflik antara masyarakat Dayak dan Madura pada saat itu memakan korban hingga ratusan orang.
Seorang pemuda Dayak melihat rumah milik orang Madura dibakar dekat Sampit, Kalimantan, 25 Februari 2001. Konflik antara masyarakat Dayak dan Madura pada saat itu memakan korban hingga ratusan orang.
Diperbarui pada Jumat, 17 November 2017, 08:00 WIB.
Sebuah tempayan ditaruh di tengah ruangan, beberapa orang mengelilinginya. Seorang tetua adat yang menjadi panyangohotn (imam) merapalkan doa, memohon pertolongan pada roh penunggu desa yang disebut panyugu alaman.
Tepung tawar juga disediakan dalam mangkuk, sebagai simbol kepala dingin dan hati sejuk. Ritual adat Dayak Salako di Kalimantan Barat (Kalbar) ini menandai dimulainya pamabokng atau rapat adat membahas konflik, seperti perkelahian dan pembunuhan.
Tempayan melambangkan mulut lebar dan perut besar dapat menelan segala sesuatu yang jahat. Orang-orang yang berkumpul mulai bermusyarawah, mencari jalan terbaik agar konflik bisa diselesaikan secara damai.
Kearifan lokal tersebut dituliskan Simon Takdir, antropolog Dayak lulusan University The Atheneo, Manila, dalam publikasi berjudul, “Menemukan Jalan Transformasi Konflik”, bersama sejumlah peneliti lain, yang diterbitkan pada 2010.
Adat perdamaian ala Dayak dilakukan untuk mencegah atau menyelesaikan konflik agar harmonisasi kehidupan tetap terjadi.
Perdamaian itu harus ditandai dengan ritual adat agar Jubata (Tuhan), awo pamo (arwah para leluhur), dan roh lain serta segenap isi alam mengetahui telah terjadi perdamaian antara kelompok yang bertikai.
Konflik bernuansa etnis antara Dayak-Madura – dan sejumlah di antaranya melibatkan etnis Bugis dan Melayu – telah terjadi beberapa kali di Kalimantan Barat.
R. Masri Sareb Putra dalam “Dayak Djangkang: From Headhunters to Catholic” memapar kronologis konflik berdarah dalam rentang 1950 hingga 2001.
Dia mencontohkan ketika pada 1979 di Samalantan, Kabupaten Sambas, seorang petani dibunuh hanya karena melarang pelaku memotong rumput di halaman rumahnya.
Kasus itu segera memicu perkelahian massal yang menewaskan 21 orang dan puluhan rumah terbakar.
Mencegah terulangnya peristiwa berdarah ini, didirikan Tugu Perdamaian di Kecamatan Samalantan.
Itu hanya sebagian kecil dari sejarah panjang konflik komunal, sehingga Kalbar disebut “laboratorium konflik” bagi mereka yang ingin mempelajarinya dan menemukan cara-cara penyelesaian.

Menggali pengalaman
Kearifan tradisi di Kalbar kini sedang dikumpulkan untuk menemukan formula bersama dalam menangani konflik, termasuk kemungkinan diadopsi dalam Hukum Humaniter Internasional (HHI).
Palang Merah Internasional (ICRC) kantor Jakarta bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kamis, 16 November 2017, menggelar diskusi multipihak untuk memberikan pengetahuan bagi ICRC tentang situasi terkini serta menggali sumbangan adat istiadat lokal dan penerapannya pada lingkup lebih luas.
“ICRC ingin menggali pelajaran penting dari pengalaman Kalimantan Barat sebagai wilayah konflik masa lalu, sehingga bisa berkontribusi untuk kewaspadaan dan mitigasi di waktu mendatang,” kata Jessica Sallabank, networking delegate ICRC, kepada BeritaBenar.
Rina Rusman, legal adviser ICRC Jakarta memaparkan, sejumlah norma adat di berbagai belahan dunia bisa diadopsi dalam HHI, sejauh bernilai universal, dan memberi manfaat bagi parapihak yang berkonflik.
Misalnya hukum perang tradisional memperbolehkan tawanan dikunjungi rohaniwan (Kerajaan Mataram), izin menulis dan bekerja (sehingga Frederick de Houtman menghasilkan kamus Melayu-Belanda semasa ditawan Kerajaan Aceh), dan larangan membunuh tawanan (Kerajaan Maluku).
Kristianus Atok, ahli antropologi lulusan Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam forum itu, menyebutkan banyak norma Dayak yang relevan berkontribusi dalam HHI.
Dia memberi contoh tradisi pamabakng dalam komunitas Dayak Salako atau Kanayatn sebagai sarana penyelesaian konflik secara kultural, berupa ritual dengan memohon pertolongan Sang Penguasa Alam.
“Sayangnya tahap berikutnya jarang dilakukan yakni pebahaupm, musyarawah lintas agama dan etnis sebagai kelanjutannya,” kata Kristianus, dosen Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak.
Tradisi bahaupm perlu terus dipromosikan sebagai wahana komunikasi antarpihak untuk menemukan solusi bersama, tambahnya.
Dari perspektif Madura — etnis yang pernah terlibat konflik dengan komunitas Dayak dan Melayu di masa lalu – Abdul Latif Bustami, peneliti dari Universitas Negeri Malang, mengatakan konflik itu dipicu oknum yang keluar dari nilai budaya yang diajarkan sejak kecil.
Padahal etnis Madura menganggap Kalimantan sebagai rampak naong beringin korong — pohon beringin pemberi tempat berteduh.
Norma-norma Madura perlu terus dipromosi di antaranya menyebut seseorang dengan manosa yang berarti manusia tanpa label, karena labeling terlalu hirarkis memunculkan stigma merendahkan manusia lain.
“Sensus tahun 2010 menyebutkan hampir 40 persen orang Madura ada di Kalimantan Barat, istilahnya untuk nyarek asep atau mencari nafkah. Mereka menyebut Kalimantan sebagai cebe deje atau Jawa bagian Utara,” kata Abdul.
Silkus 30 tahunan
Potensi konflik di Kalbar telah berulangkali diingatkan Guru Besar Sosiologi Universitas Tanjungpura Pontianak, Syarif Ibrahim Alqadrie.
Dia mencatat hingga kini sudah terjadi empat lingkaran kekerasan rasial dalam kurun 30 tahunan, berturut-turut sejak 1900-an, 1930-an, 1960-an dan 1990-an.
Ibrahim menganalisis, siklus 30 tahun berikutnya pada 2020. Hipotesis ini berdasarkan empat kali kerusuhan besar dalam durasi 30 tahunan.
Direktur Indonesia Conflict and Peace Study Network (ICPSN) itu berpendapat, konflik dapat ditangkal dengan membangun karakter multikultural, saling menghargai dan menghormati perbedaan, serta menghilangkan anasir-anasir fitnah dan permusuhan.
Dalam versi yang diperbarui ini penyebab konflik di Samalantan tahun 1979 telah dikoreksi.