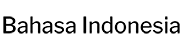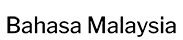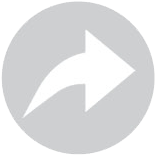Korban Konflik Aceh Masih Mencari Keadilan
2015.08.25
 Seorang aktivis mahasiswa berorasi saat berunjukrasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di ibukota Banda Aceh, hari Jumat, 14 Agustus 2015, untuk mendesak Pemerintah Aceh memperhatikan nasib para korban konflik. (BeritaBenar)
Seorang aktivis mahasiswa berorasi saat berunjukrasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di ibukota Banda Aceh, hari Jumat, 14 Agustus 2015, untuk mendesak Pemerintah Aceh memperhatikan nasib para korban konflik. (BeritaBenar)
Rukaiyah (42) masih ingat ketika seorang adiknya meminta izin kepada ibu mereka untuk mengantar kawannya, padahal peristiwa itu telah berlalu 13 tahun. Hari itu, 29 Mei 2002, sekitar pukul 20:00 WIB, adiknya Mahyuddin bin M. Yunus (15) pamit, tetapi tak pernah kembali hingga sekarang.
Tak ada firasat apa-apa pada keluarga besar Rukaiyah saat Mahyuddin pergi dengan kawannya menggunakan sepeda motor, karena sudah biasa dilakukan kedua sahabat karib yang duduk di kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rukaiyah mempunyai enam saudara perempuan dan empat laki-laki.
Itulah pertemuan terakhir Mahyuddin dan keluarganya. Keesokan harinya, dia tidak pulang. Keluarga Rukaiyah mendatangi rumah teman Mahyuddin. Kedua remaja itu tidak pernah tiba di rumah teman Mahyuddin.
Sejak itu, kedua keluarga ini berusaha mencari keberadaan anak-anak mereka. Tapi, Mahyuddin dan temannya bagai lenyap ditelan bumi. Mereka juga minta jasa “orang pintar” untuk mencari tahu keberadaan Mahyuddin. Dari terawangan “orang pintar”, diketahui Mahyuddin dan rekannya terjebak razia yang dilakukan aparat keamanan. Beberapa pos aparat sempat didatangi. Hasilnya nihil.
“Setelah berbulan-bulan kami mencari tanpa hasil, ibu mulai sakit-sakitan dan sering termenung,” tutur Rukaiyah kepada BeritaBenar di Banda Aceh, Sabtu, 22 Agustus.
Apalagi setahun sebelumnya, adiknya yang lain, Muhammad Amin (17), tewas ketika terjadi baku tembak antara pasukan keamanan pemerintah dan gerilyawan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di kawasan Cot Keu’eung, Kabupaten Aceh Besar.
“Sepengetahuan kami, Amin bukan tentara GAM, tapi hanya mendukung saja,” kata Rukaiyah, yang terlihat cukup tegar saat bercerita kejadian tragis menimpa terhadap kedua adiknya.
Komunitas korban konflik
Setahun setelah Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani perjanjian damai di Helsinki, ibukota Finlandia, 15 Agustus 2005, untuk mengakhiri konflik bersenjata selama tiga dekade di Aceh, Rukaiyah dan sejumlah warga korban konflik mendirikan Komunitas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KKP HAM) Aceh Besar.
Dia ditunjuk sebagai ketua. Rukaiyah mengaku tidak ingin lagi jadi ketua, karena sejak tahun 2009 ia telah terpilih sebagai Sekretaris Jenderal “Kagundah” (Keluarga Orang Hilang) Aceh – komunitas tempat berkumpul keluarga orang yang hilang saat konflik Aceh.
“Tapi korban konflik yang jadi anggota KKP HAM tetap memaksa saya duduk sebagai ketua. Saya tidak bisa menolak. Apalagi kerja di Kagundah dan KKP saling berkaitan,” jelasnya.
KKP HAM menjalin kerjasama dengan beberapa organisasi pembela HAM. Mereka memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas anggota memahami HAM, mendata korban baik yang dilakukan aparat keamanan maupun gerilyawan GAM, serta mengorganisir keluarga korban.
Pendampingan terhadap korban konflik juga dikerjakan Nurjubah (40) di Kabupaten Aceh Utara. Ia sendiri merupakan korban konflik. Ayahnya sempat ditangkap tentara dan ditahan dua minggu, tahun 1990. Perempuan aktivis ini mulai terlibat dalam misi kemanusiaan sejak Aceh masih dilanda kekerasan bersenjata. Dia sering mendatangi pos-pos aparat keamanan bila ada warga yang diculik.
Karena seringnya mendampingi keluarga korban, Nurjubah harus mengungsi ke Kota Lhokseumawe selama lima tahun hingga terwujudnya kesepakatan damai antara pemerintah dan GAM. Meski tinggal di Lhokseumawe, ia tetap bekerja mendampingi keluarga korban penculikan atau penangkapan.
Perempuan yang aktif pada lembaga Jaringan Perempuan untuk Keadilan (JARI) Aceh menjelaskan, dalam setiap pertemuan dengan keluarga korban konflik, mereka tetap mengharapkan keadilan dan kebenaran diungkapkan.
“Mereka ingin tahu kenapa bapak mereka dibunuh. Kenapa suaminya dibunuh dan siapa yang melakukannya. Mereka masih mengharapkan pelaku dapat diadili karena selama 10 tahun perdamaian hak mereka belum terpenuhi,” tutur Nurjubah kepada BeritaBenar, Senin 24 Agustus.
Qanun KKR
Para korban konflik mengharapkan Qanun Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akhir tahun 2013, segera diimplementasikan untuk memberikan keadilan bagi mereka.
KKR adalah perintah Perjanjian Damai Helsinki dan Undang-undang Pemerintahan Aceh. Dalam qanun disebutkan bahwa KKR mengungkap kekerasan yang terjadi dan membantu rekonsiliasi antara pelaku dengan korban sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi atas kebenaran, keadilan dan mendapatkan reparasi.
Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda menyatakan Qanun KKR belum dapat dilaksanakan karena tergantung pada pemerintah pusat.
“Memang benar qanun itu sudah disahkan oleh DPR Aceh, tapi pelaksanaannya perlu persetujuan pemerintah pusat,” katanya.
Kementerian Dalam Negeri pernah mengirim surat klarifikasi kepada Gubernur Aceh terkait Qanun KKR. Dalam surat tanggal 1 April 2014 yang didapat BeritaBenar disebutkan bahwa Qanun KKR Aceh “bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”
Menteri Dalam Negeri kala itu Gamawan Fauzi menggarisbawahi bahwa Qanun KKR baru dapat dilaksanakan setelah Undang-undang (UU) KKR terbentuk. Tetapi UU KKR yang pernah ada telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006.
Namun Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian, menyebutkan pihaknya belum menerima surat klarifikasi itu, padahal waktunya sudah setahun lebih. Dia mengaku tidak tahu alasannya surat tersebut tak diterimanya, sementara aktivis pembela HAM sudah mendapatkannya.
“Secara resmi kami tidak menerima surat itu. Biasanya surat klarifikasi Mendagri soal qanun selalu didisposisikan ke Biro Hukum karena kami yang menanggapinya,” tutur Edrian, kepada BeritaBenar, Sabtu, 22 Agustus lalu.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang dihubungi beberapa kali untuk konfirmasi tak mengangkat telepon.
Pemerintah dianggap tak serius
Direktur Eksekutif Koalisi NGO HAM Aceh, Zulfikar Muhammad, menyebutkan kalau benar Pemerintah Aceh tidak menerima klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri seperti dikatakan Edrian, maka “sesuai aturan qanun itu sudah bisa diimplementasikan.”
Zulfikar meyakini berlarut-larutnya pelaksanaan KKR di Aceh karena tidak seriusnya Pemerintah Aceh menjalankan perintah undang-undang karena “boleh jadi mereka yang berkuasa di Aceh sekarang terlibat pelanggaran HAM.”
“Harapan korban adalah segera dilakukan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi karena selama 10 tahun sudah perdamaian di Aceh tak membawa dampak baik bagi mereka,” katanya kepada BeritaBenar, Senin, 24 Agustus 2015.
Lembaga pembela HAM dan komunitas korban konflik sudah melakukan pendataan dan verifikasi jumlah korban sehingga diharapkan dapat mempermudah kinerja KKR. Malah ada data yang telah diserahkan ke DPRA dan Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Menurut dia, jika tidak ada penyelesaian pelanggaran HAM di Aceh, berarti pemerintah telah mengabaikan hak-hak korban karena mereka berhak tahu kebenaran, keadilan dan pemulihan.
Korban merasa pelaku kebal hukum dan dikhawatirkan bisa menyebabkan muncul pelanggaran baru di masa mendatang karena tidak ada efek jera dari perbuatan yang telah mereka lakukan, ujar Zulfikar.
“KKR dan pengadilan HAM harus segera dibentuk di Aceh. Bagi kami korban, hukum harus ditegakkan. Kalau keadilan tak ada, boleh jadi ada keluarga yang dendam dan konflik baru akan muncul lagi,” ujar Rukaiyah.