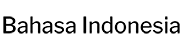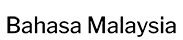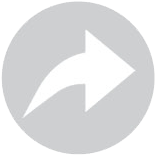Korban Bom Thamrin Berjuang Atasi Trauma, Keterbatasan Fisik
2020.01.15
Jakarta
 Dwi Siti Rhomdoni, korban aksi terorisme bom Thamrin tahun 2016 lalu, saat diwawancara di Starbucks, Thamrin, Jakarta, 13 Januari 2020.
Dwi Siti Rhomdoni, korban aksi terorisme bom Thamrin tahun 2016 lalu, saat diwawancara di Starbucks, Thamrin, Jakarta, 13 Januari 2020.
Dwi Siti Rhomdoni sedang menunggu pesanan kopinya di gerai Starbucks yang terletak di samping pusat perbelanjaan Sarinah, di wilayah Thamrin, Jakarta Pusat, tepat minggu itu empat tahun lalu, ketika seorang lelaki meledakkan diri sekitar dua meter darinya. Perempuan yang saat itu berusia 33 tahun itu pun terlempar dan tertimpa benda-benda yang berjantuhan.
Sempat tak sadar diri, Dwi kemudian bangun dan melihat keadaan porak poranda. Ia juga mendengar samar teriakan minta tolong datang dari orang di sekitarnya. Ada yang berlumuran darah. Beberapa paku tertancap di dada orang yang berdiri di depan dia.
“Kuping saya berdengung, pandangan saya berkabut, kepala saya pusing,” ujarnya ditemui BeritaBenar di Starbucks yang sama, Januari 2020.
“Saya hanya terlintas kalau saya ngga mau mati di sini,” kata dia.
Delapan orang tewas, yang terdiri dari empat pelaku dan empat warga sipil pada kejadian 14 Januari 2016, yang disebut sebagai serangan pertama di Asia Tenggara yang diklaim oleh kelompok ekstrim Islamic State (Negara Islam), atau lebih dikenal sebagai ISIS.
Setidaknya 23 orang lainnya terluka.
Ledakan pertama diikuti oleh bom kedua yang disertai rentetan tembakan bersahutan dari arah luar. Kemudian terjadi baku tembak antara polisi dan penyerang.
Para korban mengatakan bahwa mereka masih berjuang mengatasi trauma dan hidup dengan sisa luka fisik yang mereka alami.
Selama sekitar setahun, Dwi, yang mengalami patah servikal leher, memar di dada kiri dan kaki, masih tidak mempunyai keberanian menginjakkan kakinya ke Starbucks.
Tidak mudah
Dwi mengatakan tak mudah untuk memulihkan psikisnya karena hidupnya berubah 180 derajat. Ia tak bisa lagi bekerja normal sehingga memutuskan berhenti dari tempat kerja.
“Tiap hari saya marah sama keadaan, saya tidak siap lihat TV dan saya takut bagaimana menjadi seorang difabel. Tidak bekerja tapi harus biayain keluarga, akibatnya saya berhutang selama beberapa tahun,” ujarnya.
Titik balik pada dirinya terjadi ada awal 2017 saat dirinya dipertemukan dengan mantan narapidana teroris, Kurnia Widodo, dalam acara yang diinisiasi Aliansi Indonesia Damai (AIDA), lembaga berbasis di Jakarta yang bertujuan memberdayakan para korban terorisme.
Pada awalnya dendam masih menyelimuti, ia tidak mau melihat wajah sang mantan perakit bom itu ataupun mengajaknya ngobrol. "Saya memilih berpura-pura ikhlas padahal benci sekali,” papar Dwi.
Saya berkata “Bener ga sih Anda minta maaf? Jangan-jangan hanya di mulut saja. Anda punya pilihan untuk tidak melakukan tapi kenapa dilakukan,” ucapnya kesal.
“Anda ucapkan Allahu akbar saat mengebom sementara saya ucapkan Allahu akbar saat ada bom menimpa saya,” ujar Dwi kepada Kurnia.
Baru 2019, Dwi dapat memaafkan pelaku. Ia mengaku ingin hidup lebih tenang daripada harus diselimuti oleh rasa benci.
“Tidak ada ujung kebaikan dan yang ada malah nambah sakit. Saya melihat kesungguhan dari para napi terorisme ini ingin berubah dan meminta maaf dari hati yang paling dalam. Jadi saya memaafkan setelah melalui proses panjang,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh korban lainnya, Agus Kurnia, 28, yang mengatakan sejak kejadian bom itu, ia merasa trauma melewati kawasan Sarinah dan sekitarnya.
“Karena kosan saya di Kampung Bali, ya saya harus menyebrangi lokasi itu. Awalnya takut tapi saya lawan. ‘Masa iya saya harus mutar ke HI, kan capek kalau jalan kaki?’” paparnya.
Ia juga kerap kali berprasangka buruk terhadap orang yang membawa ransel ataupun kabel-kabel.
“Pernah suatu kali ada koper ditinggal di bandara, saya langsung ngumpet di balik tembok dan lapor ke petugas. Gak tahunya itu milik seorang kakek-kakek sedang ke toilet lama betul,” ujarnya.
Serpihan bom mengenai gendang telinga kirinya. Akibatnya, ia tidak lagi bisa mendengar jelas. Ia mengeluhkan sering pusing, bahkan terkadang suka pingsan.
“Jantung saya deg-degan dan telinga saya sakit, berdengung. Saya lebih senang menyepi sekarang.”
Agus bersama adiknya, Muh. Nurman Permana, sedang menyebrang di dekat pos polisi, ketika ia mendengar ledakan bom di Starbucks kala itu. Namun memilih meneruskan berjalan karena berpikir itu hanya gas meledak.
Namun beberapa menit berjalan beberapa langkah, bom kedua meledak tepat di depannya. Ia hanya berjarak beberapa meter dari pelaku. Ia terhempas, pandangannya berkunang. Ia jatuh kemudian lari ke arah Gedung Bawaslu, sementara adiknya ke arah Tanah Abang.
Kepala bagian kirinya terluka, berdarah, kaki dan tangannya lecet-lecet. Ia berjalan sempoyongan tapi tak ada yang menolong.
Sampai kemudian ia bertemu dengan tetangganya yang membawanya ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta.
Beruntung
Meskipun demikian, baik Dwi maupun Agus merasa lebih beruntung dibandingkan korban lainnya.
"Korban lainnya lukanya lebih parah. Ada korban luka bakar 70 persen. ada yang matanya buta, ada yang patah rahang dan korban yang cacat sehingga tidak bisa bekerja lagi," kata Dwi.
Dwi mengatakan bersama 13 korban bom Thamrin lainnya, mereka tergabung dalam Yayasan Penyintas Indonesia (YPI).
Tiga belas dari korban aksi serangan di Thamrin itu telah mendapat kompensasi berdasarkan putusan pengadilan 2018 atas terdakwa Aman Abdurrahman, pimpinan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) kelompok militan terafiliasi ISIS, terpidana mati yang terbukti berada di belakang sejumlah aksi teror di Indonesia termasuk bom Thamrin.
Ke-13 penyintas tersebut mendapatkan kompensasi antara Rp28 juta hingga sekitar Rp202juta.
Menurut Dwi, korban yang tidak menerima kompensasi memilih melupakan karena sudah tidak ada lagi tersangka yang disidangkan atas peristiwa itu.
"Kesehatan lebih utama dari uang, berapapun banyaknya kompensasi tak dapat menggantikan keadaan korban sekarang. Apalagi yang sudah lanjut usia atau cacat akibat bom, pasti memilih ini tidak terjadi," kata dia.
Hal yang sama diungkapkan Agus.
“Kalau boleh memilih saya tidak mau menjadi korban bom. Bantuan apapun tak dapat menggantikan luka batin dan fisik saya,” ucapnya.
Ia berharap pemerintah bisa memikirkan nasib ke depan para korban bom dengan memberikan pekerjaan tetap yang tidak terancam dipecat. “Masih banyak korban lainnya yang belum mendapat bantuan di luar sana, saya ini hanya lebih beruntung banyak dibantu,” kata laki-laki yang bekerja sebagai pegawai restauran.
Salah satu korban bom Kedubes Australia tahun 2004, Nanda Olivia Daniel, 40, mengaku belum mendapatkan kompensasi apapun dari pemerintah karena aturannya belum disahkan Presiden.
“Tidak ada pilihan lain selain menunggu assessment karena kami termasuk korban masa lampau. Pemberian kompensasi belum berlaku surut ke bawah karena terganjal aturan. Kami akan terima berapapun jumlahnya,” kata Nanda.

Menunggu Peraturan Pemerintah
Menurut Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtyas, belum rampungnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban menghambat pemberian bantuan kepada korban.
PP itu sendiri memang sudah ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 1 Maret 2019, namun direvisi demi mengatur mekanisme kompensasi dan ganti rugi agar bisa diberikan kepada para korban terorisme di masa lalu maupun di luar negeri.
“Kami tidak bisa mengeksekusi karena belum di tandatangani Presiden. Kasihan para korban sudah menunggu, Kami berharap revisi ini cepat selesai agar pembayaran bisa segera dilakukan,” ujarnya ketika dihubungi BeritaBenar.
“Nantinya, akan diatur mekanisme bantuan terhadap korban luka berat, ringan atau keluarga yang meninggal dunia,” terangnya.
PP ini merupakan turunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Sepanjang 2019, LPSK telah membayarkan kompensasi 21 korban bom dengan total jumlah Rp1,7 miliar. Saat ini, LPSK baru bisa membantu meloloskan kompensasi bagi korban terorisme yang terjadi sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terbit.
LPSK mencatat, pada 2018-2019 terdapat 595 korban bom sudah terlayani dan mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Sementara khusus jumlah total korban bom masa lampau mencapai 800-an orang. Setidaknya 250 orang diantaranya sudah terlindungi dan mendapat bantuan dari LPSK.
“Bantuannya berupa perawatan medis dan psikologis juga. Kami sudah bekerja sama dengan berbagai rumah sakit,” paparnya.
Mereka hanya perlu melengkapi persyaratan sebagai korban antara lain bukti surat keterangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan bukti rekam medis dari dokter atau rumah sakit.
Sementara itu, Kepala BNPT, Suhardi Alius, mengatakan pihaknya sudah mengurus korban termasuk memperhatikan anak-anaknya melalui kordinasi dengan kementerian terkait.
“Kami beri bantuan psikologi juga untuk anak-anaknya, bantuan untuk usaha dan lainnya yang bisa dikerjakan BNPT,” ujarnya.