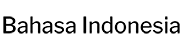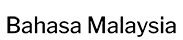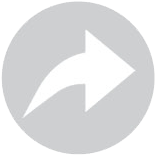Indonesia luncurkan program penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu
2023.06.27
Banda Aceh dan Jakarta
 Presiden Joko Widodo meluncurkan program pelaksanaan penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, Selasa 27 Juni 2023.
Presiden Joko Widodo meluncurkan program pelaksanaan penyelesaian non-yudisial terhadap pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu, Selasa 27 Juni 2023.
Pemerintah Indonesia pada Selasa meluncurkan program untuk memberikan pemulihan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia masa lalu yang terjadi selama beberapa fase paling kelam dalam sejarah Indonesia.
Program penyelesaian non-yudisial bagi pelanggaran hak asasi manusia berat ini mencakup beberapa pelanggaran terburuk yang terjadi antara tahun 1965 dan 2003, ketika Indonesia mengalami pergolakan politik, pemberontakan separatis, dan kekerasan massal.
Dalam acara peluncuran yang bertempat di Rumoh Geudong di Pidie, Aceh — yang disebut-sebut sebagai tempat penyiksaan pada masa konflik — Presiden Joko "Jokowi" Widodo menekankan pentingnya pemulihan bagi para korban.
“Luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Saya memutuskan agar pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang akan berfokus pada pemulihan hak korban tanpa menegasikan penyelesaian yudisial,” kata Jokowi.
Konflik separatis di Aceh berakhir dengan ditandatanganinya pakta perdamaian antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005.
Tahun lalu, sebuah tim yang ditunjuk oleh pemerintah mengidentifikasi 12 peristiwa antara tahun 1965 dan 2003 sebagai “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” yang dilakukan oleh pasukan keamanan di seluruh negara.
Kasus-kasus tersebut mencakup beberapa episode kekerasan negara yang paling terkenal dalam sejarah modern Indonesia, seperti pembunuhan massal terhadap tersangka komunis pada tahun 1965-1966, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi pada tahun 1997-1998, serta penyiksaan dan pembunuhan terhadap sipil oleh aparat keamanan selama konflik Aceh.
Pemerintah Jokowi telah mendukung langkah-langkah rekonsiliasi dan kompensasi untuk mengatasi pelanggaran tersebut.
Namun demikian, aktivis dan kelompok korban mengkritik pemerintah karena gagal membawa pelaku ke pengadilan atau memberikan kompensasi yang memadai kepada para penyintas.
Beberapa kasus telah diinvestigasi oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, namun belum ada yang diproses oleh Kejaksaan Agung.
Pada upacara di Aceh tersebut, delapan korban dan kerabat korban pelanggaran HAM masa lalu menerima sertifikat pemulihan secara simbolis dari presiden.
Mereka termasuk Akbar Maulana, seorang siswa SMA yang ayahnya ditembak dan dilukai oleh aparat keamanan saat terjadi kerusuhan di Aceh pada tahun 1999.
“Ayah pergi ikut karena penasaran, lalu ditembaki, kemudian tiarap dia, waktu itu saya belum lahir, hanya diceritakan,” ujar Akbar di hadapan Presiden.
Akbar berterima kasih atas dukungan pemerintah, antara lain berupa beasiswa dari tingkat vokasi hingga perguruan tinggi dan asuransi kesehatan.
Kehilangan kewarganegaraan
Penerima lainnya adalah Yaroni Suryo Martono, pria berusia 80 tahun yang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya saat belajar di luar negeri setelah kudeta gagal yang dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia.
Diperkirakan 500.000 orang tewas dalam pembersihan anti-komunis berikutnya dan para pendukung Presiden Sukarno saat itu diasingkan setelah penggulingannya oleh Jenderal Suharto.
Pada usia 22 tahun, Yaroni belajar di sekolah menengah di Cekoslowakia dengan beasiswa dari pemerintah Indonesia, yang mengharuskannya bekerja untuk negara selama tiga tahun setelah lulus.
“Saya tidak bisa kembali. Saya dan 16 teman-teman lainnya dicabut paspornya karena kami tidak mau menandatangani persetujuan atas terbentuknya pemerintahan baru,” kata Yaroni menceritakan kenangannya kepada Jokowi.
Sudaryanto memiliki pengalaman serupa. Dia belajar di sebuah lembaga koperasi di Moskow dengan beasiswa dari Departemen Koperasi dan Transmigrasi Indonesia. Tapi dia gagal dalam tes penyaringan yang menuntutnya untuk mencela Sukarno.
“Saya tidak bisa memenuhi skrining karena saya harus mengutuk Bung Karno dan saya tidak menerima itu. Seminggu kemudian paspor saya dicabut, dan tidak bisa pulang,” kata Sudaryanto.
Dia tinggal di Moskow dan mendapat dukungan dari pemerintah Rusia untuk menyelesaikan pendidikan dan pekerjaannya. Sudaryanto menjadi dosen dan dekan di Universitas Koperasi Rusia. Dia mengatakan dia baru bisa mengunjungi Indonesia setelah tahun 2000.
Dia mengatakan berencana untuk menjadi warga negara Indonesia lagi. “Memang direncanakan mau jadi WNI. Saya sudah punya 3 orang cucu juga. Istri saya dari Rusia, belum tentu mau (jadi WNI) namun saya yakin kalau diyakinkan bisa,” ujar Sudaryanto.
Namun Yaroni tidak tertarik untuk mengklaim kembali kewarganegaraannya. Dia mengatakan dia heran dengan tawaran itu dan tidak berniat menerimanya.
“Saya tidak pernah mengira ini terjadi di masa saya masih hidup karena bersejarah. Saya sekarang bukan apa-apa sudah tua, tapi mungkin untuk nanti bersejarah untuk generasi muda lainnya,” kata dia.
Menjelang kunjungan Jokowi ke Aceh, kelompok hak asasi manusia dan masyarakat Aceh mengecam pihak berwenang karena menghancurkan Rumoh Geudong, yang berdiri di lokasi upacara hari Selasa.
Orang Aceh melihat Rumoh Geudong di Kabupaten Pidie sebagai simbol kebrutalan militer Indonesia selama operasi kontra-pemberontakan mereka.
Seorang pejabat setempat mengatakan rumah tersebut dihancurkan untuk menghapus kenangan menyakitkan dan sebuah masjid akan dibangun di lokasi tersebut atas permintaan para korban dan kerabat mereka.
Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam dan memiliki partai politik lokalnya sendiri, berkat skema otonomi yang diberikan pada tahun 2002 untuk menenangkan tuntutan kemerdekaan.
Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International di Indonesia, menyebut pemulihan non-yudisial sebagai “proses setengah hati.”
“Ini jelas tidak membebaskan negara dari kewajibannya untuk menegakkan hak korban atas kebenaran dan hak mereka untuk menerima kompensasi penuh dan efektif atas penderitaan mereka,” kata dia dalam sebuah pernyataan.