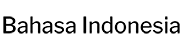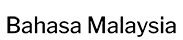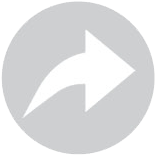Toleransi Diangkat dalam Aksi Hari Perempuan Internasional
2017.03.08
Jakarta
 Para aktivis membawa poster berisi tuntutan perempuan saat aksi Women's March di Jakarta, 4 Maret 2017.
Para aktivis membawa poster berisi tuntutan perempuan saat aksi Women's March di Jakarta, 4 Maret 2017.
Toleransi menjadi isu utama yang diangkat peserta aksi unjuk rasa di Jakarta dalam memperingati Hari Perempuan Internasional tahun ini.
Salah satu yang disuarakan panitia aksi Women’s March Jakarta, Sabtu, 4 Maret 2017, adalah menuntut agar masyarakat Indonesia kembali ke budaya toleransi dan menghormati keberagaman.
“Indonesia dibangun berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Aku berkulit coklat, kamu berkulit putih. Saya mungkin Agnostik atau Kristen atau Katolik. Jangan lihat identitas berdasarkan SARA saya, tapi lihatlah saya sebagai Warga Negara Indonesia, sebagai manusia untuk membangun peradaban yang sama,” ujar Ririn Sefsani, panitia pelaksana yang aktif di Kemitraan Partnership for Governance, kepada BeritaBenar.
“It doesn’t matter what’s your religion. Yang paling penting adalah prinsip universal tentang kemanusiaan dan hak asasi manusia,” tambahnya.
Ririn menilai sentimen atas nama agama semakin menguat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini, menurutnya, justru menjauhkan agama dari nilai-nilai cinta kasih perdamaian.
“Itu yang kami mau dorong, supaya toleransi dan keberagaman terbangun kembali,” katanya.
Peran perempuan dalam merawat toleransi, lanjut Ririn, sangat besar. Dari rumah, perempuan bisa mengajarkan keluarga tentang toleransi.
Pada aksi berbeda yang digelar untuk memperingati Hari Perempuan Internasional, Rabu, 8 Maret 2017, isu toleransi kembali muncul.
Nisa Yura dari Komite Aksi International Women’s Day 2017 mengatakan setidaknya selama 15 tahun belakangan, tindakan intoleransi menguat dari kelompok fundamentalis atau intoleran.
“Semakin lama semakin menguat, sehingga sangat berdampak pada perempuan,” katanya kepada BeritaBenar.
“Masalah intimidasi dan diskriminasi terhadap perempuan juga terjadi dan dialami perempuan minoritas, baik itu minoritas secara orientasi seksual, identitas gender, atau minoritas secara kepercayaan.”
Yang lebih mengkhawatirkan, ujar Nisa, kelompok-kelompok intoleran itu juga kemudian masuk ke berbagai lembaga formal, sehingga kebijakan yang dihasilkan bersifat diskriminatif terhadap perempuan.
“Banyak kebijakan diskriminasi di Indonesia yang juga menyasar langsung ke identitas gender perempuan, mengatur cara berpakaian perempuan atau mengatur soal jam malam,” ujarnya.
Menurut dia, toleransi harus menjadi peran semua orang, dan semua pihak. Tapi perempuan dengan pengalamannya yang paling merasakan dampak dari lunturnya toleransi itu sendiri.
“Perempuan harus berperan dalam menyuarakan ataupun menularkan kepada masyarakat nilai-nilai toleransi dan menghargai sesama,” ujarnya.
Komisioner Komnas Perempuan, Masruchah, mengatakan kasus-kasus intoleransi menguat karena ada praktik yang dilakukan kelompok intoleran sehingga dikhawatirkan dapat memecah belah bangsa.
“Dalam konteks kehidupan beragama, seluruh agama bicara soal toleransi. Tuntutan yang mencuat (di kalangan aktivis) memang penting membangun kesadaran masyarakat,” kata dia saat BeritaBenar meminta tanggapannya.
Peran perempuan, menurutnya, amat strategis dalam melakukan pendekatan kepada anak-anak dan keluarga.
“Mulai sekarang perlu mengembangkan diskusi dari rumah hingga ke ruang publik tentang dampak terorisme dan intoleransi dalam kehidupan,” jelasnya.
Di pusaran kelompok radikal
Terkait berkembangnya radikalisme di kalangan perempuan, Ririn mengatakan hal itu adalah produk dari doktrin budaya yang menempatkan perempuan sebagai kelas nomor dua.
“Lantas perempuan didoktrin untuk kemudian menjadi alat mereka melakukan perjuangan yang sarat dengan kekerasan,” tegasnya.
Fenomena ini terjadi, tambahnya, karena perempuan masih butuh ruang untuk mendapatkan pendidikan politik yang lebih baik.
“Perempuan menjadi obyek paling strategis dan mudah ditaklukkan atas nama relasi kuasa. Makanya kenapa muncul kelompok radikal menggunakan perempuan,” ujar Ririn.
Sedangkan, Nisa menilai fenomena ini muncul karena hasil dari diskriminasi dan intimidasi pihak-pihak intoleran terhadap perempuan.
“Mereka memanfaatkan kaum perempuan karena (aksi mereka) tidak akan disangka untuk melakukan tindakan terorisme, sehingga lebih mudah untuk melancarkan apa yang mereka rencanakan,” jelasnya.
Budaya patriarki, ujar Nisa, juga menyumbang peran terhadap fenomena ini.
“Perempuan selama ini hasil konstruksi budaya dimana laki lebih dominan. Saya pikir banyak perempuan yang mengikuti kelompok-kelompok intoleran atau radikal karena ikut laki-laki yang ada di sekitarnya, apakah itu pasangannya atau ayahnya,” jelas Nisa.
Sedangkan, menurut Masruchah, perempuan yang terlibat dalam aksi teror hanya dijadikan alat politik kelompok tertentu.
“Karena itu gerakan perempuan harus bergandengan tanpa melihat suku, agama, atau ras, untuk memimpin gerakan toleransi, perdamaian dan antiradikalisme,” pungkasnya.
Akhir tahun lalu, polisi menangkap beberapa perempuan karena diduga terlibat aksi terorisme. Malah, seorang perempuan yang ditangkap itu disiapkan untuk menjadi pelaku aksi bom bunuh diri.