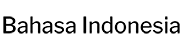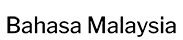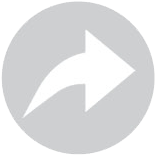Riset Radikalisme Diprotes Perkumpulan Homeschooling
2019.12.04
Jakarta
 Dari kiri ke kanan: Pendiri Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) Moi Kusman, Ellen Nugroho, dan Annette Mau dalam jumpa pers di Jakarta, 3 Desember 2019.
Dari kiri ke kanan: Pendiri Perkumpulan Homeschooler Indonesia (PHI) Moi Kusman, Ellen Nugroho, dan Annette Mau dalam jumpa pers di Jakarta, 3 Desember 2019.
Lina Sormin tak menyangka cita-citanya bersama suami untuk memberi pendidikan anak di Sekolah Rumah (SR) atau homeschooling akhirnya jadi kenyataan. Perisakan yang diderita si sulung justru membuatnya bertekad mewujudkan mimpi itu.
Lina awalnya memasukkan si sulung yang merupakan anak berkebutuhan khusus ke sebuah sekolah Katolik di Bogor, Jawa Barat, agar bisa membantunya meraih masa depan.
Namun sejak kelas 1, putranya justru kerap dirisak teman-temannya, yang awalnya hanya dianggap lazim oleh Lina.
Hingga suatu ketika, “kepalanya sampai diinjak oleh teman-temannya,” ujar Lina kepada BeritaBenar saat ditemui di Jakarta, Selasa, 3 Desember 2019.
Karena pengaduan ke kepala sekolah tidak ada solusi, Lina memutuskan mengeluarkan anak sulungnya beserta sang adik dari sekolah itu dan memberikan homeschooling.
“Kami belajar sendiri, mencari sendiri. Ternyata lebih menyenangkan dan anak-anak saya bisa lebih memperdalam minatnya. Yang pertama senang komputer, yang kedua senang menggambar,” ujarnya.
“Lagipula sistem pendidikan kita terlalu memaksakan proses menghapal, bahkan minat anak tidak difasilitasi. Sekolah sampai sore itu ujung-ujungnya hanya menghapal saja.”
Lain halnya dengan Naning Sri Wulan yang memilih SR buat anaknya karena prihatin dengan sistem pendidikan nasional yang terlalu banyak mata pelajaran.
Keputusan tersebut telah dipertimbangkan Naning dan sang suami yang berprofesi sebagai programmer sejak anak masih berusia satu tahun.
Mereka pun berinisiatif mencari cara melalui internet dan mendapatkan banyak literasi dari Amerika Serikat.
“Saya mengajar anak saya. Kalau tidak bisa seperti Bahasa Inggris, kami les,” ujar Naning.
Keuntungan didapat antara lain dari segi biaya karena untuk memasukkan anak ke sekolah sesuai standar perlu biaya tinggi.
Lewat SR, Naning bisa berhemat dan uang dialokasikan buat menghabiskan waktu bersama keluarga dengan pelesiran dan menjalani hobi.
“Suami saya hobi diving, anak juga. Kami mengambil sistem unschooling, learning by doing. Kami belajar Fisika, Biologi, dan Matematika saat diving. Kami menghitung regulator untuk bisa mengapung misalnya. Lalu baca kompas. Ilmunya langsung diterapkan,” ujarnya.
“Saya hanya butuh 15 menit mengajar anak saya, karena sistemnya kan one on one.”
Karena itu, ketika ada hasil riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta baru-baru ini yang menyatakan 10 dari 53 SR terindikasi mudah terpapar radikalisme dan intoleransi, Lina dan Naning terkejut dan tak bisa terima.
Menurut Lina, selama ini SR yang berbasis pendidikan keluarga disalahpahami masyarakat.
“Banyak yang bertanya homeschooling mana? Berapa biayanya? Itu sudah salah. Memang sistemnya belum memadai. Anak-anak saya kalau mau ujian harus ke PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat),” ujar Lina.
Naning mengaku heran dengan hasil riset karena menurutnya, radikalisme bisa masuk lewat mana pun.
“Saya kan bercadar ya. Kalau yang belum kenal akan mengira saya eksklusif. Saya salafi dan salafi sering dipojokkan,” tuturnya.
“Dalam Islam, kami wajib taat kepada imam yakni presiden, karena presiden sekarang tidak melarang berbuat apa yang kita yakini. Demo pun dilarang oleh ulama-ulama kami karena berpotensi menimbulkan kerusuhan.”
Dikritik
Riset PPIM dilatarbelakangi kasus bom bunuh diri terhadap tiga gereja di Surabaya pada Mei 2018 yang melibatkan orang tua yang diduga tak mengirimkan anak-anak mereka ke sekolah formal dan mendidik sendiri di rumah.
Penelitian mengambil sampel 53 SR di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, dan Padang.
Mereka dikategorikan dalam dua kelompok, yakni berbasis agama dan non-agama. Untuk berbasis agama, terbagi lagi menjadi dua: Kristen dan Islam.
Kategori Islam pun dibagi lagi menjadi dua; salafi-eksklusif dan salafi-inklusif. Dari jumlah itu, 10 SR tergolong dalam salafi-eksklusif.
Dalam kategori salafi-eksklusif, riset menilai anak mengalami pengucilan lebih besar karena saluran untuk punya keterikatan dengan komunitas rendah sehingga dinilai mudah terpapar paham radikal.
Kerentanan itu akan bertambah besar jika tidak adanya sejumlah parameter yang digunakan SR antara lain tidak adanya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia.
Koordinator Perhimpunan Homeschooler Indonesia (PHI) Ellen Nugroho dalam jumpa pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, memprotes hasil riset tersebut.
Dia mengklaim 329 keluarga anggota PHI yang tersebar di 23 provinsi hingga akhir Oktober 2019 justru mensyaratkan pernyataan sikap setia pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI.
Ellen menilai hasil riset itu tak lepas dari definisi RS yang masih muncul kesalahpahaman di masyarakat dan pemerintah.
Menurut Permendikbud No. 129/2014, SR adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas, dimana pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal.
“Dalam sejarahnya, SR berarti pendidikan berbasis keluarga, bukan lembaga. Kalaupun ada penelitian tentang SR harus dibedakan SR sebenarnya dan persepsi masyarakat tentang HS yang saat ini bias sekali,” kata Ellen.
“Kami berharap peneliti tidak menerima begitu saja persepsi masyarakat. Jika seperti ini sampel yang dipilih PPIM UIN, maka tidak merepresentasikan homeschooling tapi lembaga pendidikan nonformal. Salah sasaran.”
Untuk itu, PHI menolak klaim PPIM UIN bahwa anak yang tidak sekolah formal lebih besar potensinya terkena paham radikal.
“Riset-riset terdahulu menunjukkan bahwa anak yang belajar di sekolah formal dan lembaga pedidikan nonformal pun rentan terpapar intoleran dan radikalisme,” ujarnya.
Tidak generalisir
Project Manager PPIM UIN, Didin Syafruddin, menyebutkan riset bersifat kualitatif melalui serangkaian observasi, wawancara, dan penggalian dokumen.
PPIM, lanjutnya, juga mengundang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Asosiasi Sekolah Rumah dan Pendidikan Alternatif (Asah Pena) untuk memberikan masukan tentang homeschooling terkait data dan kebijakan sebelum melakukan penelitian.
“Saya sadar ternyata banyak lembaga SR. Dari sisi prosedur, kami melakukan tahap prariset agar PPIM memiliki pandangan lebih dalam lagi soal SR. Rata-rata muncul pertanyaan soal pertanggungjawaban, termasuk civic accountability,” ujar Didin.
“Kami dari awal tidak bermaksud menggeneralisir semua SR radikal. Yang kami wawancara 53 keluarga, termasuk lima keluarga pejabat. Jumlah ini jauh berbeda dari peserta PHI.”
Menurutnya, temuan riset membuktikan radikalisme dan intoleransi bisa masuk lewat apa saja, termasuk pendidikan anak.
Tak boleh diterapkan
Pengamat terorisme, Nasir Abas, menilai hasil riset itu tak boleh diterapkan secara pukul rata, bahkan terhadap keluarga salafi.
“Malah yang salafi menolak untuk menentang pemerintah. Mereka menjadikan pemerintah sebagai ulil amri (pemimpin),” ujarnya kepada BeritaBenar.
Menurutnya, keluarga pelaku teror bom Surabaya bukan pengikut salafi, dan tidak memberikan SR kepada anaknya.
“Mereka pikirannya mau jihad perang. Tidak bersekolah itu yang mudah terpapar,” katanya.
Pendapat ini selaras dengan apa yang pernah disimpulkan polisi tentang suami-istri Dita Apriyanto-Puji Kuswati yang dengan keempat anaknya melakukan bom bunuh diri di tiga gereja di Surabaya, Mei 2018, menewaskan seluruh anggota keluarga itu dan delapan orang lainnya, disamping melukai 40-an lainnya.
"Mereka ngakunya home schooling, tetapi tidak. Mereka hanya menerima doktrin-doktrin dari orangtuanya, dengan video-videonya, dengan ajaran-ajaran yang diberikan," kata Kapolda Jawa Timur, Irjen Machfud Arifin, seperti dikutip di liputan6.com.
Tanggapan pemerintah
Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Subi Sudarto, mengatakan SR adalah metode pendidikan yang tetap harus terlembagakan dalam satuan pendidikan nonformal.
"Selama tidak didaftarkan ke satuan, tidak dikontrol oleh dinas pendidikan kabupaten/kota, berarti tidak terdata dan tidak terdeteksi. Bagaimana pemerintah mau hadir?" ujarnya saat diminta tanggapannya.
"Yang salafi eksklusif tidak terdeteksi dalam satuan kita.”
Sedangkan SR yang sudah terlembaga, tambahnya, pemerintah otomatis bisa mengontrol dan peserta didik mendapatkan hak-haknya.
"Indikatornya bagaimana memperkuat pendidikan karakter anak. Di kurikulum ada yang mengajarkan perilaku dan Pancasila. Itu yang digunakan dalam indikator penelitian PPIM," pungkasnya.