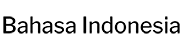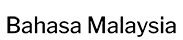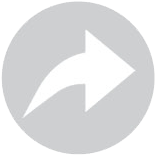Kebebasan Berekspresi dan Beragama Masih Stagnan
2018.05.21
Jakarta
 Sejumlah kelompok Muslim melakukan prostes menuntut dipenjarakannya gubernur Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, atas tuduhan penistaan agama, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 13 Desember 2016.
Sejumlah kelompok Muslim melakukan prostes menuntut dipenjarakannya gubernur Jakarta saat itu, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, atas tuduhan penistaan agama, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 13 Desember 2016.
Reformasi yang telah berlangsung dua dekade banyak membawa perbaikan dalam kebebasan politik, pers dan berorganisasi, namun kebebasan berekspresi dan beragama di Indonesia dinilai belum sepenuhnya lebih baik dibandingkan masa Orde Baru, demikian analis.
"Kualitasnya (kebebasan ekspresi) bisa dikatakan stagnan," tutur peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris kepada BeritaBenar di Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.
Syamsuddin merujuk pada sejumlah tekanan dan laporan hukum yang masih terjadi dan menimpa beberapa pihak, seperti kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dan putri mantan Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri.
Keduanya didemo sekelompok massa dan dilaporkan ke polisi setelah dinilai menista agama.
Selain itu adalah pembubaran dan pelarangan sejumlah diskusi dan pemutaran film di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya film “Senyap” yang membahas tentang peristiwa Gerakan 30 September 1965.
"Kebebasan masih di tatatan prosedural dan institusional, seperti pemilihan umum langsung oleh rakyat. Tapi soal tata kelola pemerintahan yang mendukung kebebasan berekspresi belum berubah," tambahnya.
Hal sama disampaikan Direktur Eksekutif The Indonesia Institute, Adinda Tenriangke Muchtar, dengan menyebutkan tak jauh berbeda dengan era Soeharto, pemerintah bahkan masih membuka ruang dalam pembatasan kebebasan berekspresi tersebut.
Ia merujuk pada keberadaan aturan semacam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap dijadikan sebagai landasan memidanakan seseorang.
"Masih ada aturan yang digunakan satu pihak, untuk kepentingannya, menekan pihak lain," ujar Adinda.
"Setelah 20 tahun reformasi, seharusnya tak ada lagi peraturan yang malah memasung kebebasan berekspresi."
Butuh ketegasan
Pendapat para pengamat itu seperti sejalan dengan data rilisan Badan Pusat Statistik (BPS) 2016 yang dikeluarkan September tahun lalu, yang menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia secara nasional terus menurun.
Pada 2016, indeks demokrasi Indonesia berada di angka 70,9, atau turun dari tahun sebelumnya yakni 72,82 atau 2014 yang sebesar 73,04.
Angka ini dimaknai sebagai indeks demokrasi Indonesia berkualitas sedang. Adapun indeks disebut baik jika nilai lebih dari 80.
Tolok ukur indeks ini adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.
Selain kasus Ahok dan kemudian Sukmawati, yang puisinya dianggap menista agama Islam , beberapa kasus pengekangan kebebasan lain juga terjadi di Indonesia.
Di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, misalnya, seorang dokter diintimidasi dan dipaksa meminta maaf setelah mengunggah status yang dinilai melecehkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Berikutnya adalah penyerangan terhadap pengikut Ahmadiyah di Kuningan dan Cirebon di Jawa Barat, dan pembubaran kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) di Kalimantan.
"UU seharusnya bukan memberi ruang ancaman, tapi justru melindungi dan menjamin hak privasi masyarakat,” tambah Adinda.
Terkait munculnya gerakan kelompok yang mengintimidasi kebebasan beragama itu, Sekretaris Jenderal Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (NU) Marzuki Wahid menilai karena pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi fasilitator yang baik untuk keberagaman berekspresi dan beragama.
"Pemerintah belum begitu tegas," katanya, "serta masih adanya fenomena agama yang dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu."
Hal inilah, tambah Marzuki, yang membuat kelompok intoleran mendapat ruang hidup setelah reformasi.
Pada zaman Soeharto, semua kelompok yang dianggap menghalangi kelanggengan kekuasaannya ditekan, termasuk kelompok radikal keagamaan.
"Mereka kan muncul setelah reformasi. Dan terus berkompetisi untuk mendapat pengaruh," lanjutnya.
Meski dibumbui kemunculan kelompok semacam FPI usai reformasi, Marzuki menilai secara umum kebebasan beragama di Indonesia tergolong membaik selepas zaman Soeharto.
"Seperti mulai adanya pengakuan terhadap Konghucu dan kini penghayat keyakinan," katanya.
Nasib minoritas Tionghoa
Pemerintahan Soeharto, memang terhitung represif terhadap etnis minoritas Tinghoa, seperti keharusan berasimiliasi dengan kebiasaan Indonesia. Salah satu wujudnya dengan mengganti nama dengan "warna" Indonesia.
"Meski mereka tidak benar-benar dilarang berpolitik di Orde Baru, namun mereka sendiri pada dasarnya takut untuk berpolitik," kata sejarawan Yayasan Nabil, Didi Kwartanada.
"Mungkin karena trauma, karena selalu menjadi kambing hitam, seperti peristiwa 1965."
Apalagi etnis Tinghoa menjadi korban penjarahan ketika terjadi kerusuhan menjelang tumbangnya pemerintahan Orde Baru.
Namun kondisi itu, kata Didi, membaik selepas Soeharto lengser. Hak-hak mereka perlahan diakui dan setara dengan warga etnis lain di Indonesia, salah satunya dengan mengakui Hari Raya Imlek.
"Kendati sekarang mulai muncul lagi lewat sentimen ras yang dimunculkan politikus lewat pemilihan umum," ujar Didi, "tapi secara umum sentimen