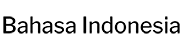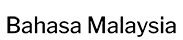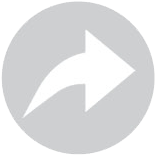Aktivis Dukung MA Tolak Gugatan atas Peraturan Menteri Soal Kekerasan Seksual di Kampus
2022.04.19
Jakarta
 Aktivis dari gerakan anti kekerasan perempuan Indonesia melakukan protes mengecam pelecehan dan kekerasan seksual di kampus-kampus, di depan gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta pada 10 Februari 2020.
Aktivis dari gerakan anti kekerasan perempuan Indonesia melakukan protes mengecam pelecehan dan kekerasan seksual di kampus-kampus, di depan gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta pada 10 Februari 2020.
Aktivis Indonesia mendukung keputusan Mahkamah Agung pada Selasa (19/4) yang menolak gugatan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Gugatan dilayangkan oleh Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, sebuah organisasi komunitas masyarakat Sumatra Barat, yang meminta Mahkamah Agung (MA) meninjau kembali penerbitan peraturan tersebut yang dinilai permisif terhadap hubungan seksual di luar nikah.
Peneliti dan aktivis dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Johanna Purba, mengatakan alasan sikapnya mendukung keputusan MA ini, karena angka kasus kekerasan seksual di kampus cukup tinggi.
“Bahkan setelah Permendikbudristek (Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) ini diterbitkan, kita masih dengar adanya kasus-kasus kekerasan seksual di kampus dari awal 2022 ini,” kata Johanna kepada BenarNews, Selasa.
Johanna mengatakan rumusan peraturan menteri ini berpihak pada korban.
Selain adanya aturan soal consent (persetujuan) yang rinci dan pengecualiannya, peraturan ini juga cukup rinci mengatur kewajiban dan keterlibatan kampus beserta civitas akademikanya dalam upaya pencegahan, penanganan, hingga pemulihan, ungkap Johanna.
“Lalu poin penting lainnya adalah hak kelompok disabilitas juga diperhatikan di sini, dari mulai akomodasi, sistem pelaporan, pendampingan, dan sebagainya sudah mengatur agar korban kekerasan seksual dengan disabilitas dijamin haknya,” paparnya.
Sambutan positif terhadap keputusan MA ini juga disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Chatarina Muliana Girsang.
“Kita bersyukur, berdasarkan info yang termuat pada website kepaniteraan MA yang kami terima, MA telah menolak permohonan hak uji materiil terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021,” ujar Chatarina, “lahirnya Permendikbudristek ini adalah momentum untuk menyatukan langkah kita untuk melindungi warga pendidikan tinggi dari ancaman kekerasan seksual yang merusak masa depan.”
Saat ini kementerian tengah menunggu rilis putusan dimaksud dari MA, kata Catharina dalam pernyataan yang dimuat di situs kementerian.
Belum diketahui apa alasan MA menolak gugatan itu. Upaya untuk menemukan dokumen keputusan di situs lembaga itu tidak membuahkan hasil.
Peraturan yang dikeluarkan Agustus tahun lalu itu mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mencakup verbal, nonfisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
Beleid pasal itu juga mengkategorikan tindakan menyampaikan ucapan rayuan dan lelucon bernuansa seksual, diskriminasi atau pelecehan tampilan fisik sebagai kekerasan seksual.
Permendikbud menyatakan bahwa kekerasan seksual termasuk “menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuh seseorang pada tubuh korban tanpa persetujuan korban” dan “membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban.”
Namun peraturan itu banyak ditentang oleh kalangan Muslim konservatif, yang menilai peraturan itu justru melegalisasi perbuatan asusila dan seks di luar nikah.
Tidak setuju
Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kurniasih Mufidayati, tidak menampik jika partainya menjadi pihak yang sedari awal meminta Permendikbudristek Nomor 30/2021 itu dicabut dan direvisi.
PKS menginginkan peraturan menteri tersebut tidak hanya mengatur soal kekerasan seksual “tanpa persetujuan korban”, namun juga mencakup perilaku seksual dengan persetujuan (consent).
“Dulu saat Permendikbudristek dikeluarkan teman-teman fraksi PKS dari komisi 10 sudah banyak menyampaikan pendapat (seperti ini),” kata Mufidayati kepada BenarNews, Selasa.
Partai itu juga menjadi satu-satunya dari sembilan fraksi di DPR yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang akhirnya sah menjadi undang-undang pada 12 April lalu.
Johanna, sebagai peneliti, mencermati bahwa pihak-pihak yang menolak ini berfokus pada istilah “persetujuan korban”. Jadi, kata dia, yang menolak menganggap kalau kata “consent” ini membuka peluang untuk adanya hubungan seksual secara bebas di kampus.
“Sangat disayangkan karena fokus pihak yang menolak ini sebetulnya keluar dari tujuan Permendikbudristek ini yaitu untuk melindungi korban kekerasan seksual di kampus,” ucapnya.
“Consent di sini kan justru salah satu unsur penting untuk membuktikan apakah memang terjadi kekerasan seksual atau tidak dan untuk menghindari kriminalisasi orang yang memang tidak bersalah. Hampir serupalah dengan UU TPKS, ada unsur persetujuan korban yang diakui di sana.”
Johanna mengakui belum semua kampus punya regulasi yang komprehensif dan berpihak korban untuk menangani kasus kekerasan seksual ini.
“Makanya penting ada satu payung hukum dari Permendikbudristek ini yang selaras dengan UU TPKS dan bisa menjangkau semua kampus,” ujarnya.
Pada bulan November 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim mengatakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi sudah menjadi pandemi.
Survei kementerian itu pada 2020 menemukan bahwa 77 persen dosen mengakui kekerasan seksual terjadi di kampus, namun hanya sepertiganya saja yang terlapor, kata Nadiem. Adapun mayoritas korban kekerasan seksual adalah perempuan.
“Kita sedang berada dalam situasi darurat kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bisa dibilang situasi gawat, kita bukan hanya mengalami pandemi COVID-19, tetapi juga pandemi kekerasan seksual,” kata Nadiem waktu itu.
Nadiem mengatakan, fenomena tersebut terjadi akibat kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
“Jadi kita ini dalam fenomena gunung es yang kalau kita garuk-garuk, terlihat sudah kasus kekerasan seksual di berbagai kampus,” ujar Nadiem.