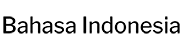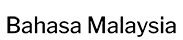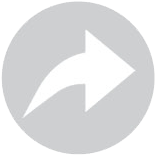Ketika Dolly Ditutup dan PSK Mencari Pelanggan di Jalanan
2017.01.06
Surabaya
 Pada foto tertanggal 19 Juni 2014 ini, dua staff laki-laki sebuah rumah bordil di Dolly menginstruksikan para PSK untuk menutup wajahnya ketika wartawan mengambil foto dan video dari luar.
Pada foto tertanggal 19 Juni 2014 ini, dua staff laki-laki sebuah rumah bordil di Dolly menginstruksikan para PSK untuk menutup wajahnya ketika wartawan mengambil foto dan video dari luar.
Mengenakan baju bergambar kupu-kupu bertuliskan beauty¸ Anggi menikmati sebatang rokok saat dia sedang santai di tempat kosnya. Sesekali, senyum mengembang di bibirnya.
Perempuan 30-an tahun asal Jember ini merupakan salah seorang dari 1000 lebih pekerja seks komersial (PSK) di lokalisasi Jarak dan Dolly yang ditutup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, 27 Juli 2014 silam.
Sebelumnya, di kawasan tersebut terdapat sekitar 800 wisma. Dalam semalam, konon perputaran uang di tempat itu bisa mencapai Rp 2 miliar.
Anggi bekerja sebagai PSK di lokalisasi yang pernah menjadi terbesar Asia Tenggara itu sejak 2003 hingga 2007. Ia sempat berhenti pada 2008 hingga 2012, tapi kemudian bekerja lagi hingga lokalisasi Dolly ditutup.
Sehari, Anggi bisa melayani 5 hingga 10 tamu. Jika dinominalkan mencapai Rp350 ribu hingga Rp1 juta dalam sehari. Tarif sekali kencan antara Rp70 ribu hingga Rp100 ribu.
Pascapenutupan Jarak dan Dolly, Anggi ingin mengubah hidup dengan tidak lagi menjadi PSK.
Namun, dengan bekal pendidikan kelas 2 SMP, sulit baginya mendapatkan pekerjaan sehingga memilih menjadi PSK jalanan di Surabaya.
Menjadi PSK saat ini diakui Anggi tidak semudah ketika lokalisasi masih buka. Dalam seminggu, bisa mendapatkan seorang tamu adalah hal yang luar biasa.
“Saat ini, mendapat satu tamu seminggu sudah bagus. Tarif sekali kencan, saya memasang Rp. 200 ribu,” ujar ibu dua anak ini kepada BeritaBenar, Selasa, 3 Januari 2017.
Seluruh pendapatan perbulan dikumpulkan Anggi terlebih dahulu sebelum dikirim ke kampung halaman untuk biaya kedua anaknya.
“Sebulan saya harus menyisihkan Rp300 ribu untuk kost dan kebutuhan sehari-hari. Jika sudah mendapatkan minimal Rp1 juta, saya baru kirim ke kampung,” jelasnya.
Astuti (45) dan Sulastri (50), dua eks PSK Dolly lain juga pernah mencoba beralih profesi.
Astuti pernah bekerja sebagai penjahit dengan pendapatan sehari Rp20 ribu hingga Rp30 ribu.
Sedangkan, Sulastri pernah bekerja sebagai baby sitter dengan upah sebesar Rp1 juta. Dia juga pernah berjualan nasi, namun itu tak bertahan lama karena minimnya pendapatan dan harus berkejaran dengan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).
“Dengan pendapatan segitu jelas tidak cukup untuk hidup. Mau tidak mau kami harus kembali menjadi PSK,” kata Astuti sembari menghisap rokoknya.
Tidak dibayar
Profesi PSK jalanan, membawa konsekuensi bagi ketiganya. Selain harus bermain petak umpet dengan Satpol PP, mereka tidak bisa memilih tamu.
Ketiganya juga tidak bisa rutin memeriksa kesehatan seperti saat lokalisasi masih buka. Selain keterbatasan biaya, mereka malu ketika ditanya pekerjaan oleh perawat Puskesmas atau rumah sakit.
Persoalan lain adalah menghadapi pelanggan nakal, yang terkadang tak mau membayar hingga melarikan diri.
“Saya sering mengalami itu. Pernah pria kabur sampai lupa membawa telepon genggamnya. Jadi telepon genggam itu sebagai ganti ongkos servis,” terang Anggi sambil tertawa.
Meski mematok harga Rp200 ribu sekali kencan, tarif tersebut bisa dinego dengan kesepakatan kedua pihak. Untuk pelayanan, mereka melakukan di hotel atau losmen.
“Kami berkomitmen untuk tidak menerima layanan servis di Jarak dan Dolly,” cetus Astuti.
Solusi terbaik
Koordinator Paguyuban Warga Putat Jaya, Amin meminta pemerintah dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik setelah 2,5 tahun penutupan lokalisasi.
Bagi warga yang selama ini menggantungkan hidupnya dari lokalisasi harus memutar otak agar tetap hidup. Mereka adalah penyedia layanan parkir, para pedagang, dan pemilik rumah musik.
Amin berharap pemerintah tidak melabel PSK sebagai perusak moral saja, tapi juga memikirkan susahnya mereka mencari sesuap nasi dengan latar belakang pendidikan yang minim.
Khusus untuk rumah musik, Amin meminta pemerintah tidak melarang 150 rumah musik milik warga yang masih beroperasi, karena menjadi satu-satunya sumber pendapatan mereka.
Pemilik rumah musik telah berkomitmen tidak menyediakan layanan prostitusi. Jika ada perempuan pemandu lagu - yang biasa dikenal dengan purel - di tempat karaoke, itu adalah keinginan dari perempuan itu sendiri.
Yanto, pemilik parkir di jalan Jarak membenarkan minimnya pendapatan pasca-penutupan Dolly dan Jarak.
“Dulu saya bisa memperoleh Rp400 hingga 500 ribu perhari, sekarang mendapatkan Rp20 ribu saja sudah bagus,” ungkapnya.
‘Ubah wajah’
Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengatakan kebijakan penutupan lokalisasi sudah dibarengi dengan kesiapan mengubah wajah lokalisasi. Di Jarak dan Dolly, sudah ada warga binaan dalam bidang industri rumah tangga.
Salah satunya adalah Wisma Barbara yang merupakan wisma terbesar di Dolly. Wisma ini dibeli pemerintah kota (Pemko) untuk dijadikan industri rumah tangga di bidang sepatu. Selain itu, ada 13 wisma yang dibeli Pemko Surabaya.
“Perlahan kami akan mengubah wajah Jarak dan Dolly menjadi salah satu destinasi wisata di Surabaya,” kata walikota perempuan pertama di Surabaya.
Penutupan lokalisasi dinilai sesuai dengan Perda No 7 tahun 1999, tentang larangan bangunan dijadikan tempat asusila. Risma juga ingin warga sekitar bisa mendapatkan penghasilan di luar bisnis esek-esek.
Namun harapan walikota itu tampaknya masih jauh dari terpenuhi.
Anggi, Astuti, Sulastri, dan mungkin puluhan mantan PSK Dolly dan Jarak lainnya, masih menjalankan profesinya, kali ini mencari pelanggan di jalanan Kota Surabaya.