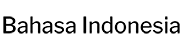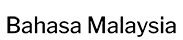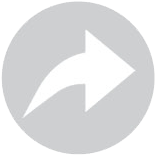Perjuangan Rakyat Papua Pertahankan Tanah Ulayat
2018.11.16
Jayapura
 Warga Papua dan Papua Barat yang menjadi korban perampasan tanah oleh perusahaan kelapa sawit melakukan unjuk rasa di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 14 November 2018.
Warga Papua dan Papua Barat yang menjadi korban perampasan tanah oleh perusahaan kelapa sawit melakukan unjuk rasa di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta, 14 November 2018.
Sejumlah suku di Papua mengadukan perampasan tanah yang kerap mereka alami pada Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), pada Kamis, 15 November 2018, mengatakan bahwa pemerintah daerah sering menjadi bagian dari permasalah karena memberikan izin tanpa persetujuan warga.
“Hutan itu, bagaikan mama bagi kami. Kalau hutan kami terus ditebang dan dibabat oleh perusahaan, bagaimana nasib anak cucu kami nanati?” kata Veronika Manimbu, perempuan asal Suku Mpur Kebar dari Kabupaten Tambrauw, Papua Barat.
Bersama Veronik, ada lima perwakilan suku lainnya yaitu Suku Moi Klasouw dan Malalilis dari Kabupaten Sorong, Suku Iwaro dari Kabupaten Sorong Selatan, Suku Mandobo dari Boven Digul, dan Suku Marind dari Kabupaten Merauke.
Mereka mengatakan gereja menjadi harapan terakhir para pemilik ulayat atas tanah ini setelah pemerintah daerah tak bisa memberikan keadilan untuk mereka.
“Pemerintah daerah bahkan menjadi bagian persoalan yang harus kami hadapi,” ungkap Veronika.
Keenam suku itu telah menjadi korban kebijakan pemerintah dan aktivitas perusahaan perkebunan PT. Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) dan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mega Mustika Plantation.
Veronika mengatakan pemberian izin dan perolehan hak atas lahan maupun kawasan hutan dilakukan tanpa persetujuan warga setempat.
Perusahaan, menurutnya, melakukan aktivitas tanpa dilengkapi dokumen legal, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dan hak guna usaha (HGU).
“Perusahaan juga melakukan pengrusakan hutan dan tempat penting sumber pangan dan mata pencaharian masyarakat,” katanya.
Warga yang sejak lama tinggal di lahan-lahan yang kemudian menjadi konflik sering kali harus berhadapan dengan aparat keamanan dalam areal yang telah dikuasai perusahaan atau institusi negara seperti pemerintah, kepolisian dan TNI.
“Akibatnya mencuat konflik masyarakat dan perusahaan, serta aksi kekerasan hingga pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara, seperti pemerintah daerah dan aparat keamanan,” ungkap Veronika.
John Gobay, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dari Franksi Otonomi Khusus membenarkan jika sebagian besar perusahaan yang menguasai tanah di daerah itu menggunakan aparat keamanan untuk pengamanan.
“Biasanya sesuai permintaan perusahaan. Sebenarnya ini memalukan. Aparat bukannya jaga masyarakat malah jaga perusahaan,” katanya seraya berharap pimpinan keamanan meninjau kembali penempatan anak buahnya di perusahaan-perusahaan itu.
Dugaan pelanggaran HAM
YL. Frangky, Direktur Yayasan Pusaka, LSM yang berkantor di Jakarta mengatakan sudah beberapa kali konflik antara masyarakat dan perusahaan di Papua berujung pada kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Salah satunya yang paling dikenal adalah kasus Wasior, yang menewaskan empat warga sipil dan lima anggota Brimbo pada 2001.
“Kasus konflik seperti ini adalah peristiwa Wasior yang juga mengakibatkan satu orang mengalami kekerasan seksual, lima hilang dan 39 orang disiksa oknum Brimob setelah PT Vatika Papuana Perkasa, perusahaan kayu di sana dituding mengingkari kesepakatan dengan masyarakat pemilik ulayat,” katanya kepada BeritaBenar.
Hingga kini, kekerasan itu masih tercatat sebagai kasus dugaan pelanggaran HAM yang belum diselesaikan pemerintah, padahal Komisi Nasional (Komnas) HAM sudah selesai melakukan investigasi dan hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung.
Yayasan Pusaka mencatat terdapat sekitar 14 perusahaan yang hampir semua bergerak di sektor kelapa sawit berkonflik dengan masyarakat adat Papua di Papua dan Papua Barat.
“Total luas lahan yang dikuasai 14 perusahaan tersebut mencapai 343.000 hektar,” kata Frangky.
Menurutnya, konflik-konflik tanah di Tanah Papua sering kali bermula dari pengalihan kepemilikan lahan yang dilakukan secara diam-diam oleh oknum tertentu, padahal lahan tersebut milik komunitas suku, bukan perorangan.
Jika di pesisir Papua, konflik lebih sering terjadi antara masyarakat adat dan perusahaan, sementara di daerah pegunungan Papua, konflik tanah kerap terjadi antara masyarakat adat dengan insitusi negara seperti pemerintah, TNI maupun Polri.
“Kami melakukan penolakan pemberian tanah seluas 90 hektar untuk TNI karena tanah itu bukan milik kepala suku. Itu milik semua orang dalam suku,” kata Ketua Solidaritas Peduli Hak Masyarakat Adat Pegunungan Tengah Papua, Steven W. Walela.
Menurutnya, penolakan pemberian tanah seluas 90 hektar untuk Kodam Cenderawasih yang dilakukan Kepala Suku Silo Karno Doga, Alex Doga, Oktober lalu, karena tanah itu “wilayah sakral dan tempat berkebun.”
Jika tanah tersebut beralih fungsi, tambahnya, akan berdampak buruk bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
Pangdam Cenderawasih yang ketika itu masih dijabat Mayjen George Supit mengatakan bahwa 90 hektar tanah tersebut akan digunakan untuk membangun markas brigade TNI.
Tak hanya memberikan tanah, kepala suku tersebut juga memberikan gelar adat kepada Jenderal Supit yang kemudian diprotes masyarakat.